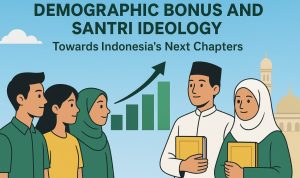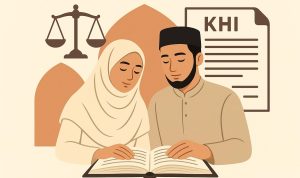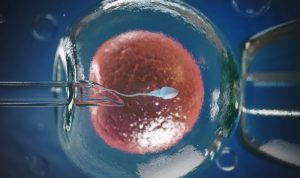Perubahan iklim global telah memperburuk ketimpangan ekologis dan sosial, terutama di wilayah pesisir yang mengalami peningkatan frekuensi banjir rob. Peristiwa ini tidak dapat sekadar dimaknai sebagai fenomena alam semata. Lebih dari itu, banjir rob merupakan manifestasi dari ketimpangan iklim yang secara langsung memengaruhi ketahanan sosial masyarakat. Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, merupakan salah satu daerah yang paling rentan terhadap dampak banjir rob akibat penurunan muka tanah, perubahan pola sedimentasi, serta eksploitasi air tanah. Dalam konteks ini, masyarakat yang terdampak tidak hanya menghadapi tantangan ekologis, tetapi juga harus beradaptasi dengan keterbatasan akses terhadap sumber daya dan kebijakan pemerintah.
Menyoal dampak banjir rob, perlu dicermati bahwa penurunan muka tanah di Sayung terjadi dengan laju yang cukup signifikan, yakni sekitar 7–21 cm per tahun. Peristiwa ini bukan sekadar akibat dari perubahan alamiah, tetapi juga diperparah oleh aktivitas eksploitasi air tanah yang tidak terkendali serta perubahan pola sedimentasi pesisir. Masyarakat yang bermukim di daerah dengan tingkat penurunan tanah paling tinggi mengalami kesulitan dalam beradaptasi, terutama kelompok ekonomi rendah yang tidak memiliki opsi untuk berpindah ke lokasi yang lebih aman. Dampak dari penurunan muka tanah ini tidak dirasakan secara merata. Kelompok masyarakat dengan tingkat ekonomi lebih tinggi dapat melakukan adaptasi fisik dan ekonomi, seperti membangun rumah panggung atau meninggikan fondasi tempat tinggal mereka. Sementara itu, kelompok yang lebih rentan justru menghadapi keterbatasan akses sumber daya serta minimnya dukungan infrastruktur dari pemerintah. Dengan demikian, ketimpangan ini tidak hanya berada dalam ranah ekologis, tetapi juga menjadi persoalan ketahanan sosial yang semakin memperlebar jurang antara kelompok masyarakat terdampak.
Banjir rob yang terjadi di Sayung bukanlah peristiwa yang sekali datang lalu berlalu, melainkan telah menjadi tantangan jangka panjang yang memengaruhi seluruh aspek kehidupan masyarakat. Dalam menghadapi realitas ini, masyarakat setempat telah mengembangkan beragam strategi adaptasi, baik dalam bentuk perubahan fisik maupun penguatan jaringan sosial. Salah satu bentuk adaptasi yang umum dilakukan adalah pembangunan rumah panggung, terutama di Desa Bedono dan Timbulsloko, yang memungkinkan warga tetap bertahan meskipun wilayah sekitar mereka terendam. Selain itu, penggunaan perahu sebagai alat transportasi semakin umum dilakukan, terutama di desa-desa seperti Sriwulan dan Surodadi, di mana jalan utama telah berubah menjadi jalur air.
Selain strategi individu, masyarakat juga berupaya mengatasi dampak banjir rob dengan pendekatan berbasis lingkungan, seperti penanaman mangrove di pesisir Sayung untuk memperlambat abrasi dan mengurangi risiko banjir. Program ini sering kali digerakkan oleh komunitas lokal yang sadar akan pentingnya perlindungan ekosistem pesisir sebagai upaya mitigasi. Dari segi ekonomi, beberapa warga yang sebelumnya bekerja sebagai petani beralih ke usaha tambak ikan dan udang, karena lahan pertanian mereka telah berubah menjadi daerah yang sering tergenang.
Namun, perlu digarisbawahi bahwa tidak semua warga mampu melakukan adaptasi secara optimal. Dengan adanya penurunan muka tanah yang terus berlangsung, strategi adaptasi yang semula dianggap cukup menjadi kurang efektif dalam menghadapi ancaman lingkungan yang semakin besar. Misalnya, tanggul-tanggul kecil yang dibuat secara mandiri oleh masyarakat untuk menghalau air semakin tidak mampu menahan genangan. Ketahanan sosial yang inklusif memerlukan intervensi kebijakan yang lebih sistematis, di mana dukungan pemerintah harus berorientasi pada peningkatan kapasitas masyarakat melalui pendekatan berbasis komunitas (community-based adaptation).
Adanya ketimpangan sosial dalam adaptasi terhadap banjir rob menegaskan perlunya kebijakan yang lebih partisipatif dan berkelanjutan. Pemerintah daerah telah melakukan sejumlah upaya seperti membangun tanggul dan memberikan bantuan sosial, tetapi langkah-langkah ini dirasa masih bersifat reaktif dan kurang terintegrasi dalam kebijakan yang lebih komprehensif.
Kesimpulan
Banjir rob di Kecamatan Sayung bukanlah sekadar masalah lingkungan, tetapi juga merupakan manifestasi dari ketimpangan iklim yang memengaruhi ketahanan sosial masyarakat. Dengan laju penurunan muka tanah yang semakin cepat, tantangan yang dihadapi masyarakat tidak hanya terkait dengan dampak ekologis, tetapi juga dengan keterbatasan sumber daya dan akses terhadap kebijakan adaptasi yang memadai. Respons masyarakat yang beragam menunjukkan potensi adaptasi yang kuat, tetapi di saat yang sama juga mengungkap ketidakadilan dalam akses sumber daya. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan adaptasi yang lebih berorientasi pada komunitas dan berbasis kelestarian ekologi agar masyarakat Sayung tidak hanya bertahan, tetapi juga dapat menjalani kehidupan yang lebih stabil di tengah perubahan iklim.
Daftar Pustaka
Fatimah, B. N., Wijaya, A. P., & Yusuf, M. A. (2023). Analisis estimasi zonasi nilai tanah di kawasan banjir rob dan pembangunan jalan tol Semarang–Demak Kecamatan Sayung Kabupaten Demak. Jurnal Geodesi Undip. https://doi.org/10.14710/jgundip.2023.40991
Kusumowardani, E. W., Wibowo, S. S., & Zukhruf, F. (2023). Analisis perubahan kecepatan pada jalan tol Semarang–Demak akibat bencana banjir rob di pesisir utara Semarang. Jurnal Teknik Sipil, 30(3), 491–493.
Suprihanto, H. D., & Susanti, R. (2023). Studi luasan genangan banjir rob akibat kenaikan muka air laut dan penurunan muka tanah di Kecamatan Sayung, Demak. Indonesian Journal of Coastal and Ocean Engineering, 5(1), 34–45. https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/ijoce/article/download/19468/11809