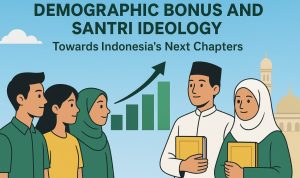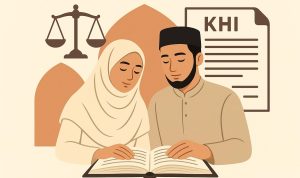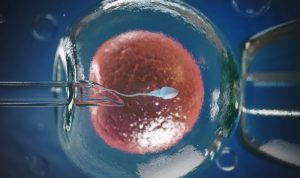Pendahuluan
Eksploitasi alam merupakan topik yang tidak pernah usang untuk dibicarakan, terutama dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah. Kekayaan ini menjadi daya tarik besar bagi investasi, pembangunan, serta percepatan ekonomi nasional. Namun, di balik kilau keuntungan ekonomi tersebut, tersembunyi realitas gelap berupa kerusakan lingkungan, perampasan ruang hidup masyarakat lokal, dan hilangnya keseimbangan ekosistem yang berdampak sistemik terhadap keberlangsungan hidup makhluk hidup, termasuk manusia.
Dalam konteks ini, penting kiranya kita membicarakan eksploitasi alam bukan semata dari sisi legalitas berdasarkan undang-undang, tetapi juga dari sisi moralitas dan etika spiritual. Hukum Islam melalui maqāshid al-syarī‘ah mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan. Begitu juga dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (3) yang menyatakan bahwa “bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Namun dalam praktiknya, asas kemaslahatan sering dikalahkan oleh kepentingan bisnis dan kekuasaan.
Esai ini bertujuan untuk mengupas eksploitasi alam secara mendalam dengan membandingkan perspektif hukum positif Indonesia dan fatwa keagamaan (terutama melalui Bahtsul Masail NU), serta merumuskan arah pengelolaan lingkungan yang adil dan berkelanjutan.
Eksploitasi Alam: Definisi dan Praktik di Lapangan
Eksploitasi alam dapat dipahami sebagai kegiatan ekstraksi atau pengambilan sumber daya alam dari bumi, baik yang berbentuk padat, cair, maupun gas, untuk kepentingan manusia. Di Indonesia, praktik ini diatur dalam berbagai peraturan, mulai dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Pertambangan, hingga UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
Namun realitas di lapangan sering kali menunjukkan bahwa praktik eksploitasi berjalan secara tidak terkendali. Contohnya adalah kerusakan lingkungan di Kalimantan akibat tambang batubara yang mengakibatkan hilangnya ribuan hektar hutan tropis, atau lubang-lubang bekas tambang bauksit di Riau yang menjadi “kuburan ekologis.” Penambangan emas di Papua pun seringkali menyisakan kubangan raksasa, meninggalkan tanah tandus, dan pencemaran sungai yang merupakan sumber kehidupan masyarakat adat.
Dampak ekologis ini diperparah oleh lemahnya pengawasan pemerintah dan seringkali abainya para pemegang izin terhadap Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Padahal AMDAL merupakan syarat penting sebelum sebuah kegiatan eksploitasi alam dilakukan.
Perspektif Hukum Islam: Antara Maslahah dan Mafsadah
Dalam Islam, tujuan hukum (maqāṣid al-syarī‘ah) dibangun atas lima prinsip utama: menjaga agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-‘aql), keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan harta (ḥifẓ al-māl). Dalam konteks eksploitasi alam, paling tidak dua aspek utama yang terdampak secara langsung, yakni keselamatan jiwa dan harta.
Fatwa Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama menegaskan bahwa eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan adalah haram. Hal ini diputuskan dalam Muktamar NU ke-33 di Jombang. Alasan utamanya adalah karena kerusakan lingkungan yang ditimbulkan menyebabkan mafsadah (kerusakan atau keburukan), yang dalam kaidah ushul fiqh dinyatakan:
“درء المفاسد مقدم على جلب المصالح”
Menghindari kerusakan lebih utama daripada menarik kemaslahatan.
Eksploitasi yang hanya menguntungkan segelintir pihak tetapi menimbulkan penderitaan bagi masyarakat luas, merusak ekosistem, dan menghilangkan keberlangsungan hidup generasi mendatang, secara prinsip bertentangan dengan ruh syariat Islam.
Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Fikih Ekonomi
Para ulama dari mazhab Maliki memandang bahwa kekayaan alam khususnya barang tambang adalah milik umum yang dikelola oleh negara demi kemaslahatan umat. Ini sesuai dengan prinsip ‘umūm al-balwā, bahwa sesuatu yang digunakan untuk kebutuhan umum tidak boleh dimonopoli oleh individu atau korporasi. Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni menyatakan bahwa sumber daya alam seperti air, api, garam, dan barang tambang merupakan barang publik dan tidak boleh dimiliki secara eksklusif.
Dengan demikian, peran negara sangat vital sebagai pengelola sumber daya alam, bukan sebagai “penjual izin.” Negara harus hadir sebagai pengatur yang adil, penjamin distribusi, serta pelindung lingkungan. Ketika negara justru menjadi fasilitator eksploitasi demi keuntungan segelintir elit atau investor, maka peran ini telah melenceng dari mandat konstitusional dan tanggung jawab syariat.
Konstitusi dan Realitas: Ketegangan antara Pasal 33 dan Liberalisasi Ekonomi
Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 jelas menyatakan bahwa sumber daya alam harus digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Namun, sejak era reformasi dan desentralisasi, banyak perizinan tambang justru dikeluarkan secara massif oleh pemerintah daerah tanpa pertimbangan ekologis yang memadai. Alih-alih menyejahterakan rakyat, praktik ini justru memperparah ketimpangan ekonomi dan kerusakan alam.
Negara terlihat permisif terhadap korporasi besar yang menambang tanpa standar ekologis, sementara masyarakat adat yang menjaga hutan selama ratusan tahun malah sering dikriminalisasi dengan tuduhan “menghalangi pembangunan.” Ketimpangan struktural ini menimbulkan pertanyaan: untuk siapa sesungguhnya eksploitasi itu dijalankan?
Eksploitasi, Etika, dan Peradaban
Eksploitasi tidak hanya menyentuh dimensi hukum dan ekonomi, tapi juga dimensi moral dan peradaban. Dalam Al-Qur’an, Allah memperingatkan manusia agar tidak berbuat kerusakan di muka bumi setelah adanya perbaikan:
“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, setelah (Allah) memperbaikinya.” (QS. Al-A’raf: 56)
Ayat ini mengandung pesan ekoteologis yang sangat kuat. Bumi adalah ciptaan Allah yang dititipkan kepada manusia sebagai khalifah. Oleh karena itu, relasi manusia terhadap alam bukan relasi eksploitatif, melainkan relasi amanah dan tanggung jawab.
Penutup: Rekonstruksi Paradigma Eksploitasi
Eksploitasi alam tidak bisa semata diukur dari sisi legalitas perizinan. Ia harus ditimbang dengan prinsip keadilan ekologis, keberlanjutan lingkungan, serta tanggung jawab spiritual manusia sebagai khalifah di bumi. Ketika praktik eksploitasi hanya didasarkan pada pertimbangan ekonomi jangka pendek dan mengabaikan kemaslahatan kolektif, maka sesungguhnya kita sedang menyemai kehancuran bagi masa depan.
Hukum Islam telah memberikan kerangka moral dan etis yang jelas, bahwa segala sesuatu yang mendatangkan kerusakan besar dan mengancam keberlangsungan hidup adalah haram. Negara, melalui perangkat konstitusi dan perundang-undangan, semestinya mengemban amanat tersebut dengan serius.