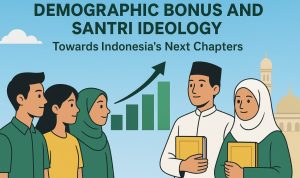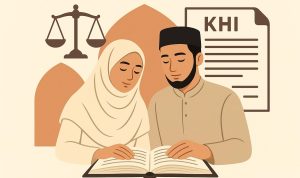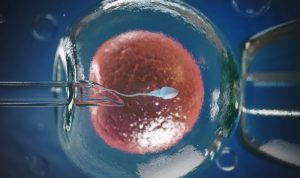Telaah keilmuan Islam telah berkembang pesat dan selalu mengikuti perkembangan zaman. Keniscayaan adanya perkembangan ini selanjutnya mengakibatkan berbagai peradaban yang selalu berkelanjutan, kemajuan di bidang teknologi, dan berbedanya cara pandang dalam menanggapi realitas kehidupan. Salah satu perkembangan keilmuan yang pada hari ini menjadi perhatian cukup luas ialah keilmuan astronomi. Pada statistik sepuluh tahun terakhir tahun 2012 sampai 2022 menunjukan bahwa ada sekitar 9,330 artikel yang membahas tentang pendekatan keilmuan astronomis.[1]Walaupun konteks perkembangan keilmuan astronomi dalam penulisan jurnal memiliki konteks untuk membicarakan wacana (isi), namun pada akhirnya tidak menutup kemungkinan keilmuan ini juga berkembang sebagai alat (metode atau nalar). Dari titik inilah, bahwa keilmuan astronomi berperan sebagai metode atau nalar, penulis akan mencoba menarasikan bagaimana ulumuddin -khususnya fiqh- berdialog dengan keilmuan astronomi dalam narasi dan wacana tahqiqul manath.
Dalam doktrin keilmuan islam, terdapat perbedaan pendapat pada syarat penguasaan keilmuan astronomi (falak, hisab) dalam diri seorang mufti. Di sana terdapat dua kubu Ulama, antara yang mengharuskan pengintegrasian keilmuan ini dalam diri seorang mufti dan yang tidak mengharuskan. An-Nawawi mengutip pendapat Ibnu Shalah, menyatakan tentang hal ini, bahwa seorang mufti disyaratkan memiliki pengetahuan cukup memadai pada keilmuan hisab (astronomi atau falak). Hal ini karena realitas (masail) yang dihadapi mufti terkadang memiliki hubungan erat dan membutuhkan keilmuan astrnomi sebagai validasi, maka baginya harus menguasai keilmuan ini.[2] Pada titik inilah saya menawarkan konsep “tahqiqul manath” sebagai penghubung antara keduanya (fiqh dan antronomi). Bagaimana keduanya saling berdialong satu sama lain.
Secara harfiah, astronomi adalah hukum atau budaya bintang-bintang. Sedang secara terminologi, keilmuan astronomi adalah ilmu yang melibatkan penjelasan dan pengamatan mengenai sesuatu yang terjadi di luar bumi dan atmosfernya.[3] Kajian ilmu astronomi mencakup benda-benda yang berada di langit dan di luar bumi, dari segi asal-usul keberadaannya, evolusi, sifat fisik, karakter pembentuknya, dan sifat kimiawinya.[4] Selain hal itu, astronomi juga memiliki andil dalam patokan arah bagi para nelayan tradisional, perhitungan waktu pasang surut air laut, musim tanam para petani, prediksi cuaca, menentukan waktu dengan berpijak pada bulan dan matahari.[5] Pada tatanan praktis dan konkrit ini, penulis akan menjembentaninya dengan ketetapatan dalam fiqh.
Hukum fiqh yang telah mapan akan selalu mengalami dan meniscayakan akan perkembangan. Kecenderungan fiqh yang bersifat pragmatis ini, menyiratkan keterbukaan terhadap keilmuan lain, baik sebagai pelengkap atau bahkan penentu hukum. Dikotomi antara keilmuan islam dan keilmuan umum akan menjadikannya hukum itu tertutup, jumud, tertahan, dan sifat konserfatif dan radikal tak diragukan lagi. Meminjam istilah Amin Abdullah, bahwa keniscayaan untuk mengintegrasikan keilmuan luar ke dalam wacana islam adalah sebuah wacana tandingan (counter discourse) dan akan menghadapi wacana ideologis lain pada setiap zamannya.[6] Penulis akan menawarkan wacana “tahqiqul manath” ini sebagai alat pembedah dialektika keilmuan islam -khususnya fiqh- dengan keilmuan strnomi.
Redefinisi Falak Dan Astronomi
Dalam kajian keilmuan islam, istilah ilmu astronomi ini dapat disepadankan dengan keilmuan “falak”. Secara teoritis, kedua ilmu ini memiliki pemaknaan yang sama, namun mengalami perbedaan seiring dengan perkembangan zaman dan munculnya teknologi yang mampu memberikan data yang lebih akurat. Dalam keilmuan klasik islam (turats), keilmuan falak dikenal dengan “ilmu hai’ah”. Sedang secara terminologi, ilmu hai’ah yaitu ilmu yang mengkaji tentang letak geometris benda-benda langit, guna menentukan jadwal melakukan suatu ibadah dan bagaimana cara mengetahui posisi benda-benda langit dari bumi.[7]
Istilah “falak” berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata “falak” yang bermakna lintasan atau orbit. Ilmu ini sering disebut dengan ilmu hai’ah, nujüm, ta’dīl, miqat.[8] Ahmad Mukhtar menyatakan bahwa ilmu falak adalah ilmu yang mengidentifikasi benda dan entitas langit dari segi bentuknya, keberadaannya, dan rotasinya. Menurutnya ilmu falak adalah ilmu yang paling dahulu dikenal manusia diantara ilmu-ilmu lain.[9]Fakhruddin Ar-Razi sebagaimana yang dikutip Susiknan Azhari, dalam, menyebut dengan istilah ilmu hisab, sebab kegiatan yang paling menonjol terkait dengan ilmu ini adalah melakukan perhitungan.[10] Badan Hisab dan Rukyat, mengistilahkan dengan ilmu hisab dan astronomi, yang diartikan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari benda-benda langit, tentang fisiknya, geraknya, ukurannya dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya.[11] Redevinisi antara kedua ilmu ini mengindikasikan bahwa objek keilmuan ini ialah sama, yaitu benda langit.
Fakultas Teks Transendental Dalam Otoritas Keilmuan Astronomi
Pada masa Nabi saw, penentuan waktu salat dikaitkan dengan fenomena astronomis saat itu (khususnya posisi matahari), hal ini dipahami dari penjelasan hadis dari Abdullah bin Amar yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa ketika Malaikat Jibril menemui Nabi saw dan mengajarkan waktu-waktu salat, waktu-waktu salat tersebut ditentukan berdasarkan gerakan matahari. Salat Zuhur dimulai sejak matahari tergelincir sampai bayang-bayang sesuatu sama panjangnya, salat Asar dimulai sejak bayang-bayang sesuatu sama panjangnya atau sejak bayang-bayang sesuatu dua kali panjangnya sampai matahari menguning, salat Magrib dimulai sejak matahari terbenam sampai hilangnya mega merah, salat Isya dimulai sejak hilangnya mega merah sampai tengah malam, dan salat Subuh dimulai sejak terbit fajar selama matahari belum terbit.[12]
Al-Qur’an sebagai teks transendental, telah memberikan isyarat keberadaan tata surya sebagai yang selalu menetap di dalam posisinya. Secara tegas Allah menyatakan bahwa “matahari akan selalu berjalan (menetap) di tempat beredarnya”.[13] Kemudian di ayat lain, Allah menjadikan bulan memiliki tempat peredaran yang bersifat menetap dan berotasi dengan kesesuaian. Sehingga bulan tersebut memiliki cahaya yang berbeda-beda di setiap malamnya, mulai dari ‘hilal’, kondisi dimana bulan hanya memiliki cahaya sangat kecil, sampai “badr”, yaitu kondisi dimana bulan bercahaya dengan sempurna, sampai cahaya itu setiap hari mengurang. Saat jumlah perbedaan cahaya dari bulan ini dijumlahkan, maka akan terdapat 28 hari. Demikian kira-kira, Allah menetapkan penanggalan dengan berbasis pada bulan yang menetap dan tidak akan berhenti, sampai pada waktu yang hanya Allah mengetahuinya, yaitu Hari Akhir (yaumul qiyamah).[14] Dari isyarat Al-Qur’an ini, dunia islam mengejawentahkannya dalam satu keilmuan yang selalu mengalami perkembangan dan pragmatisme,[15] yaitu keilmuan “falak”, dan dalam literatur lain disebut sebagai ilmu “astronomi”. Realitas astronomi yang bersifat menetap, mengindisikan satu teori keilmuan dan selalu berdialog dengan kecanggihan teknologi.[16]
Integrasi Ilmu Astronomi Sebagai Determinan Yuridis Islam Dalam Konsep Tahqiqul Manath
Untuk mengintegrasikan wacana keilmuan “astronomi” dengan ilmu fiqh (yuridis islam), satu teori ushul fiqh yang kiranya mampu menjembatani dialog antar keduanya ialah ijtihad “tahqiqul manath”. Diksi “ijtihad” ini meminjam istilah Asy-Syathibi (1388 H), bahwa ijtihad dalam tataran yang tidak akan pernah berhenti sampai datamg Hari Kiamat adalah ijtihad tahqiqul manath. Sedang tahqiqul manath secara istilah ialah proses interaksi, kontekstualisasi, indigenisasi dan vernakularisasi hukum islam dengan realitas sosial, budaya dan segala problem pada kehidupan modern ini, baik hukum itu dipastikan oleh dalil Al-Qur’an, hadits, atau ijma’.[17] . Dalam wacan ijtihad yang dipaparkan Asy-Syathibi, beliau memberikan dua tipe ijtihad. Pertama, ijtihad yang otoritasnya hanya boleh dilakukan oleh “mujtahid mutlak”. Dari ijtihad ini, lahirlah hukum yuridis fiqh, syarat berlakunya, sebab penetapannya, pencegah (mani’) hukumnya, serta ilat (titik temu) dalam penganalogiannya. Kinerja mujtahid ini telah selesai dan tidak memiliki perubahan yang signifikan. Sehingga ijtihad ini sudah tidak memiliki otoritas untuk mengurangi atau merevisi ketetapannya.[18]
Proyeksi bangunan hukum islam akan mendapatkan nilai relefansinya, jika proses aplikasi dan aktualisasi hukum (tanzilul hukmi) pada sebuah realitas bersifat tepat dan minim akan kesalahan. Bayangkan, bagaimana jika hukum tersebut diaplikasikan pada realitas dan mukallaf yang salah. Maka relevansinya akan tercederai, sehingga hukum jauh dari kata kemashlahatan. Pada titik inilah Asy-Syathibi mengenalkan model ijtihad kedua, yang dikenal dengan “Tahqiqul manath”. Ijtihad ini yang tidak mengenal waktu merepresentasikan akan kebutuhannya di setiap keadaan.[19]
Dalam konteks ijtihad pertama, ketetapan hukum telah final di tangan para mujtahid, termasuk dalam internal madzhab kita, yaitu Imam Syafi’i (204 H). Diantara keputusan hukum tersebut, dipastikan terdapat hukum yang sifatnya masih abstrak dari segi waktunya dan atribut pengaplikasiaannya. Penetapan sholat contohnya. Sebab kewajiban shalat ialah masuknya waktu shalat. Keberadaan waktu merupakan hal yang sangat dibutuhkan oleh manusia, tak terkecuali sebagai penanda waktu shalat. Seorang tidak dikatakan sah shalatnya, jika dia tidak tau secara pasti (yakin) bahwa waktu shalat telah mulai.[20] Pada titik inilah keilmuan astronomi (falak) sangat dibutuhkan sebagai penentu (tahqiq) masuknya waktu.
Tak hanya waktu shalat, berbagai hukum dalam fiqh banyak yang membutuhkan jawaban dari para astronom sebagai verifikasi. Diantaranya penentuan awal dan akhir bulan, terutama Ramadhan, Syawwal, Dan Dzulhijjah.[21], penetapan waktu gerhana rembulan dan matahari,[22] penentuan arah kiblat,[23] penentuan waktu imsak dan berbuka puasa,[24] penetapan talak yang digantungkan dengan waktu atau fenomena alam juga termasuk membutuhkan ketetapan yang akurat. Pengetahuan yang akurat akan suatu realitas (idrok al waqi’, knowledge of reality), merupakan kinerja tahqiqul manath, dalam konteks ini menggunakan keilmuan astrnomi.
Para astronom dapat berandil dalam penetapan hukum syariat yang membuhkan pendapatnya secara khusus. An-Nawawi mengutip pendapat Ibnu Shalah, menyatakan tentang hal ini, bahwa seorang mufti disyaratkan memiliki pengetahuan cukup memadai pada keilmuan hisab (astronomi atau falak). Hal ini karena realitas (masail) yang dihadapi mufti terkadang memiliki hubungan erat dan membutuhkan keilmuan astrnomi sebagai validasi, maka baginya harus menguasai keilmuan ini.[25] Internalisasi keilmuan astronomi dalam tubuh seorang mufti tentu memiliiki tantangan tersendiri dan akan membutuhkan kesungguhan dalam menekuninya. Oleh karenanya, untuk menjembataninya seorang mufti cukup menanyakan persoalan ini pada astrnomi dan astrofisikawan yang menurutnya terpercaya.[26]
Jika begitu gambaran sekilas antar kedua keilmuan ini, lalu bagaimana relasi antar kedua ilmu ini? Ini merupakan persoalan tersendiri. Relasi tersebut bersifaat paralelkah, linearkah, atau sirkularkah? Jika hubungan antara keduanya bersifat paralel maka masing-masing keduanya akan berjalan sendiri, tanpa persinggungan satu sama lain. Bentuk relasi paralel akan mengasumsikan bahwa dalam diri sebuah hukum syariat tidak membuka persiunggungan sama sekali dengan keilmuan astronomi. Sedangkan pola hubunfan linear, pada ujungnya akan mengalami jalan buntu. Sejak awal pola hubungan ini akan menempatkan salah satu dari kedua keilmuan ini akan menjadi primadona. Sebuah hukum syariat akan menepikan masukan yang ia peroleh dari keilmuan astronomi.
Seorang faqih akan menganggap bahwa keilmuan fiqh yang ia miliki sebatgai satu-satunya keilmuan yang ideal dan final. Jenis pilihan dominasi ini pada gilirannya akan mengantarkan seseorang pada kebuntuan. Karena ketertutupan ilmu fiqh bisa mengakibatkan kebuntuan dogmatis-teologis. Model pola hubungan paralel dan linear antar dua keilmuan ini dapat digambarkan sebagai berikut.
Karena keduanya sudah gugur, maka tawaran relasi ialah model sirkular, melingkar. Dimana kedua ilmu ini tidak memiliki dominasi dan hegemoni. Karena keilmuan fiqh bersifat membutuhkan nalar astronomi. Juga nalar astronomi tidak akan berguna tanpa ada validasi teks transendental. Cara berfikir, mentalitas, etos keilmuan seperti ini akan menghantarkan hukum fiqh bersifat terbuka-aktif-progresif, jauh dari kejumudan-pasif-konserfatif. Corak hubungan ini tidak mencerminkan adanya finalitas, eksklusifitas serta hegemoni.
Kesimpulan
Perilaku integrasi-interkoneksi keilmuan islam dan astronomi merupakan sebuah wacana yang telah ada sejak hukum islam masa Rasulullah. Dengan berkembangannya ilmu dan teknologi, ilmu astronomi mengalami kemajuan yang cukup signifikan dibanding pada masa Rasulullah. Penegasan kembali akan perilaku ini akan menjadi sebuah keniscayaan yang tak terbendung. Karena men-dikotomi kedua dua kutub keilmuan -ilmu agama dan umum- sama halnya menjadikannya jumud, konserfatif, dan tidak terbuka tehadap ideologi liyan. Dalam tulisan ini, penulis mencoba memberikan wacana tandingan (counter discourse), dengan pendekatan epistemology tahqiqul manath dalam literatur ushul fiqh.
Wacana epistemology tahqiqul manath ini adalah sebuah cara berfikir untuk mengaplikasikan sebuah hukum dengan realitas dunia (astronomi) dengan menggunakan keilmuan astronomi. Dengan metode ini, hukum islam akan mendapatkan relefansinya dan akan bersifat aktif-progresif. Keterbukaan hukum islam terhadap keilmuan sekuler ini dapat dilihat dengan nalar berfikir tahqiqul manath. Karena sifat dari objek hukum selalu berkembang dan selalu membutuhkan kepastian hukum, maka pengetahuan akan realitaas (idrok al waqi’, knowledge of reality) dalam tahqiqul manath menjadi keniscayaan tak terbantahkan. Pada titik inilah hukum akan menyuarakan sebuah nilai kemashlahatan bagi manusia secara kongkrit.
Relasi antar kedua ilmu ini dapat dikaitkan dengan jaringan sirkular. Dimana kedua ilmu tersebut membentuk sebuah pola pembedah suatu problematika sosial secara beriringan. Keduanya memiliki peran yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Teks fiqh sebagai validasi transendental, sedang nalar astronomi sebagai pembedah realitas astronomi (dunia). Siklus jaringan ini merupakan satu wacana baru untuk mengintegrasikan keilmuan islam dan sekuler pada tatanan teori-praktis dengan basis tahqiuqul manath.
[1] Penulis mengutip pernyataan ini dari sebuah jurnal berjudul “Pendekatan Astronomis dalam Studi Islam”, yang ditulis pada tahun 2022. Sehingga Kesimpulan sementara,kajian ilmu astronomi hingga sekarang telah memeberikan ruang tersendiri dalam perkembangan keilmuan, terutama keilmuan islam. Siti Mufarokah1, Nurul Alfudiah2 dkk, Jurnal Studi Islam, Vol. 18 Nomor 2, Desember 2022).
[2] Lihat dalam “Adabul Mufti wal Mustafti”, hal. 89 dan Al-Majmu’ Lin Nawawi, Juz.1, hal. 42. Pendapat ini merupakan pendapat kuat (ashoh), yang dipegang oleh Imam Nawawi dan Ibnu Solah.
[3] KBBI, 2022.
[4] Mega, N. (2013). Wahana Jelajah Angkasa Berbasis World Wide Telescope Sebagai Lingkungan Belajar Ilmu Astronomi. Jurnal Teknodik, (Jurnal Teknodik Vol. 17 No. 1 Maret 2013), Hal. 606-615.
[5] Rakhmadi, A. J. (2016). Khazanah Astronomi Islam Abad Pertengahan. UM Purwokerto Press.
[6] Tulisan Amin Abdullah berjudul “Dialektika Epistemologi dalam Perspektif Humanisme Islam”, sebagai pengantar dalam buku yang berjudul “Humanisme Islam, Kajian Terhadap Pemikiran Filosofis Arkoun”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. Vi.
[7] Kontribusi Al-Khawarizmi Dalam Perkembangan Ilmu Astronomi, Hasrian Rudi Setiawan, (Al-Marshod: Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu-Ilmu Berkaitan), hal. 75
[8] Kamal al-Din Husain, Ta’yin Awail asy-Syuhür al-Arabiyyah bi al- Isti’mal al-Hisab (Mesir: Dar at-Taba’ah wa an-Nasyr, 1399/1979), h. 6.
[9] Ahmad Mukhtar Umar, Mu’jam Al-Lughoh Al-Arobiyyah Al Mu’ashorohl.
[10] Susiknan Azhari, “Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern”, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007), h. 3
[11] Depag: Badan Hisab dan Rukyat, Almanak Hisab Rukyat (Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1981), h. 14
[12] Muslim Ibn Al-Hajjaj, Shohih Muslim, Vol. 1, hlm. 426, (maktabah syamilah).
[13] Qur’an Surat Yasin ayat 36
[14] Wahbah Az-Zuhaili, Tafsir Al Munir, vol. 16, hlm. 23, (maktabah syamilah).
[15] (Teori Pragmatisme dalam dunia filsafat adalah teori kebenaran yang mendasarkan diri pada kriteria tentang berfungsi atau tidaknya suatu teori pengetahuan dan lingkup ruang dan waktu tertentu. Jika suatu teori pengetahuan secara fungsional mampu menjelaskan, meramalkan, dan mengontrol suatu gejala alam tertentu, secara pragmatis teori itu benar. Tetapi, jika suatu waktu muncul teori lain yang mengkritik dan menolak teori pertama, kebenaran dialihkan kepada teori baru itu. Hal ini memberikan satu wacana akan keilmuan yang selalu berkembang dan mengalami perubahan dalam menanggapi suatu realitas, sehingga kebenaran akan teori tersebut bersifat “pragmatis”. (Aksin Wijaya, Satu Islam Raham Epistemologi, (Yogyakarta, IRCiSoD, 2020), hal. 48.
[16] Al-Qorrofi, Anwarul Buruq FI Anwail Furuq, Vol. 2, hlm. 179.
[17] Balqosim Az-Zabidi, Al-Ijtihad Fi Manathil Hukmi Asy-Syar’i, hal. 474
[18] (Asy-Syathibi, Al-Muwafaqot, vol. 5, hal. 11. (Maktabah syamilah).
[19] Ibid, Hal. 12
[20] Dalam sebuah kaidah disebutkan bahwa “Al-Ibroh Fil Ibadah Bima Fi Dzonnil Mukallaf wa Nafsil Amri” Bahwa sahnya ibadah dinilai dari dugaan (kuat) oleh mukallaf dan dengan apa yang ada dalam kenyataan. Keduanya (dugaan dan kenyataan) harus saling beriringan satu sama lainnya. Jika salah satu runtuh maka ibadah tidak dianggap sah. Lihat Fathul Mu’in, karya Zainuddin Al-Malibari, dalam maktabah Syamilah, hlm. 321.
[21] Dalam teori ilmu falak, penetapan awal bulan dapat diverifikasi dengan dua cara. Pertama model hisab (perhitungan) dan Ru’yah (melihat hilal). Di Indonesia, MUI dan NU menggunakan metode ru’yatul hilal, sedang Muhammadiyyah menggunakan model hisab dalam penentuan awal dan akhir bulan.
[22] Kendati hukumnya makruh menurut Sebagian Ulama. Lihat “Al-Mukhtashor Fi Ma’rifatis Sinin”, karya Ahmad Bin Abdulla Dahlan, hal. 31.
[23] Mengetahui masuknya waktu dan mengetahui arah kiblat merupakan sebuah syarat sah shalat yang harus terpebuhi secara penuh di dalam shalat. Tanpa keduanya saat shalat, maka tidak dikatakan sebagai shalat yang sah.
[24] Kedua waktu (imsak dan berbuka) ini harus terpenuhi oleh seorang yang berpuasa. Sehingga Ketika dua waktu ini tercederai oleh seorang yang berpuasa, maka puasanya dianggap batal.
[25] Lihat dalam “Adabul Mufti wal Mustafti”, hal. 89 dan Al-Majmu’ Lin Nawawi, Juz.1, hal. 42. Pendapat ini merupakan pendapat kuat (ashoh), yang dipegang oleh Imam Nawawi dan Ibnu Solah.
[26] Hal ini dapat diqiyaskan dengan seorang mufti yang diharuskan memferivikasi kepada seorang dokter, jika permasalahan yang dihadapi mufti tersebut membutuhkan jawaban dari ilmu kedokteran.