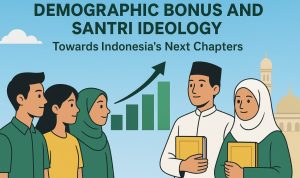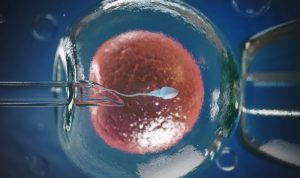Di tengah perkembangan zaman yang pesat, pernikahan bukan lagi sekadar ikatan lahir batin antara dua individu, laki-laki dan Perempuan. Melainkan juga sebagai institusi sosial yang membawa dampak luas bagi stabilitas masyarakat. Fenomena yang kerap muncul belakangan ini seperti pernikahan dini, nikah siri, sering kali menimbulkan persoalan hukum dan sosial. Tidak jarang, masalah seperti status anak, hak waris, dan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga berawal dari akad yang tidak memenuhi ketentuan agama dan hukum negara.
Bagi umat Islam di Indonesia, pembahasan mengenai pernikahan biasanya merujuk pada dua sumber utama. Pertama, fikih madzhab Syafi’i yang telah lama menjadi rujukan utama masyarakat muslim Indonesia. Kedua, Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang disusun pemerintah sebagai pedoman resmi bagi peradilan agama. Kedua sumber ini memandang pernikahan bukan sekadar kesepakatan sosial, melainkan akad sakral atau mitsaqan ghalidzan yang mengandung nilai ibadah.
Dalam pandangan fikih Syafi’i, pernikahan adalah akad yang menghalalkan hubungan suami istri, dilakukan dengan lafaz yang jelas, seperti nikah atau tazwij. Hukum asalnya adalah mubah, namun bisa berubah menjadi wajib, sunnah, makruh atau haram tergantung kondisi masing-masing individu. Tujuannya pun tidak sekadar memenuhi kebutuhan biologis secara halal, tetapi juga menjaga kehormatan diri, melanjutkan keturunan, dan membangun keluarga yang harmonis. Pandangan ini sejalan dengan definisi yang diatur KHI, yang menempatkan pernikahan sebagai sarana untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah.
Kedua sistem hukum ini sepakat bahwa suatu pernikahan tidak sah kecuali memenuhi rukun yang telah ditentukan. Lima rukun itu adalah calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi laki-laki, dan ijab qabul. Calon mempelai harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti beragama Islam, berakal sehat, baligh, dan tidak memiliki halangan pernikahan. KHI menambahkan syarat pada calon mempelai, yaitu usia minimum (19 tahun suami, 16 tahun istri) dengan izin wali jika di bawah 21 tahun. Kemudian persetujuan kedua belah pihak juga merupakan unsur mutlak, yang dalam KHI diatur harus dikonfirmasi langsung oleh Pegawai Pencatat Nikah sebelum akad dilangsungkan.
Inti pernikahan terletak pada ijab qabul, yaitu pernyataan resmi yang mengikat kedua mempelai. Dalam fikih Syafi’i, ijab diucapkan oleh wali mempelai perempuan, sedangkan qabul diucapkan oleh calon suami. KHI mengatur tata cara ini secara lebih administratif, memastikan berlangsungnya akad di hadapan saksi dan pejabat pencatat agar memiliki kekuatan hukum.
Meski pernikahan memiliki banyak unsur, keberadaan wali tetap menempati posisi yang sangat penting. Baik fikih Syafi’i maupun KHI menegaskan bahwa perempuan tidak dapat menikahkan dirinya sendiri, melainkan harus melalui wali. Wali di sini dapat berupa wali nasab, kerabat laki-laki dari jalur ayah atau wali hakim yang ditunjuk negara jika wali nasab tidak ada atau tidak memenuhi syarat. Ketentuan ini merujuk pada sabda Nabi Muhammad SAW, “Tidak sah pernikahan tanpa wali” (HR. Ahmad dan Ashabus Sunan), yang dimaksudkan untuk menjaga kemaslahatan dan kehormatan perempuan.
Selain ketentuan agama, KHI menambahkan aspek administratif berupa kewajiban pencatatan nikah. Pencatatan ini tidak memengaruhi keabsahan pernikahan dari sisi syariah, namun memiliki fungsi penting dalam perlindungan hukum. Dengan pencatatan resmi, status pernikahan, hak istri, dan status anak dapat diakui negara, sehingga meminimalkan potensi sengketa hukum di kemudian hari.
Jika dicermati, fikih Syafi’i memberikan kerangka normatif yang kuat untuk memastikan pernikahan berjalan sesuai ketentuan syariah. Sementara itu, KHI berperan menyesuaikan prinsip-prinsip syariah tersebut dengan realitas sosial dan kebutuhan hukum modern di Indonesia. Keduanya saling melengkapi: fikih memastikan sahnya pernikahan secara agama, dan KHI menjamin pengakuannya secara hukum negara.
Dengan membaca ulang makna pernikahan dari dua perspektif ini, dapat dipahami bahwa menikah bukan hanya soal memenuhi rukun dan syarat pernikahan, tetapi juga memastikan perlindungan dan kepastian hukum. Pernikahan yang ideal adalah pernikahan yang sah menurut agama, tercatat secara resmi dalam negara, dan dijalankan dengan kesadaran penuh akan tanggung jawab yang diembannya.