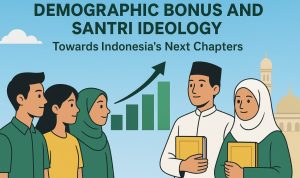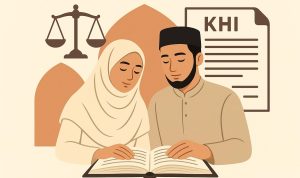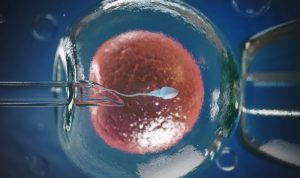Kehidupan modern ini sering digambarkan dengan perlombaan tanpa henti, obsesi pada karier, kemudahan dalam akses informasi sosial dan lain-lain. Kehidupan terasa berjalan dengan sangat cepat, perkembangan informasi yang didukung oleh kemajuan teknologi makin hari semakin membebani pikiran. Dunia dengan segala hiruk pikuknya selalu mengelilingi kita bak tiada hentinya selalu memenuhi isi kepala. Namun dibalik segala kemudahan itu, banyak dari kita yang malah merasakan kecemasan, stress, dan kehilangan identitas. Keberadaan “minuman segar” dirasa semakin kita butuhkan agar kita dapat merasakan ketenangan dan menemukan makna batin kita.
Dalam kondisi inilah, khazanah islam menawarkan “minuman segar” nya, yaitu ‘uzlah. Konsep ini semakin menemukan relevansinya bersanding dengan berbagai aliran filsafat yang belakangan ini booming seperti stoicisme. Walaupun keduanya memiliki orientasi yang berbeda, baik ‘uzlah maupun stoicisme sama-sama mengajarkan jalan menuju ketenangan batin dan pengendalian diri. Namun ‘uzlah lebih dari sekedar konsep filosofi hidup, ia merupakan salah satu tahapan perjalanan seorang hamba dalam mencapai ridlo-Nya. Maka berangkat dari problem-problem diatas, kami tertarik untuk memaparkan relevansi uzlah pada era modern ini.
Secara bahasa ‘uzlah berasal dari عزل – يعزل – عزلا yang berarti memisahkan, membatasi عَزَلْتُ الشَّيء عن غيرِه عَزْلا.[1] Sedangkan secara istilah adalah menghindari sesuatu yang tidak baik atau keluarnya seseorang dari pergaulan (berinteraksi) dengan makhluk lain (manusia) dengan menyendiri dan memutuskan hubungan, serta merasa senang/bangga dengan hal yang menakjubkan baginya[2]. Berangkat dari definisi ini, ‘uzlah mencakup dua praktik, yaitu praktik fisik menyendiri dan memutuskan hubungan dari interaksi sosial yang berlebihan serta praktik batin menghindari hal buruk dan menikmati hasil dari penyendiriannya.
‘Uzlah merupakan jalan sepi seorang hamba dalam rangka mencari ridlo-Nya. Seorang hamba harus rela meninggalkan keluarga, harta benda, serta menanggalkan seluruh gelarnya dengan menyendiri demi fokus beribadah dan melakukan segala amal kebaikan. Kisah ‘uzlah yang sering kita dengar adalah kisah Syeikh Abu Syuja’ dan Imam al-Ghozali. Keduanya merupakan ulama’ besar pada zamannya yang menanggalkan segala jabatan dan gelar demi berkonsentrasi dalam beribadah.
Para ulama’ berbeda pendapat dalam menghukumi ‘uzlah. Sebagian ada yang mensunahkan ‘uzlah dan mengutamakannya daripada berinteraksi sosial, seperti Sufyan al Tsauri dan Fudhoil bin ‘Iyad. Sedangkan kubu yang lain terdiri dari golongan tabi’in. Mereka lebih mengutamakan interaksi sosial dan memperbanyak ikatan persaudaraan supaya bisa tolong-menolong dalam kebaikan diantara mereka. Terlepas dari perbedaan hukumnya, perbedaan hukum ini timbul dari perbedaan istidlal serta konteks yang meliputi masing-masing pendapat.
Mengutip dari Hujjah al islam al Ghozali, ‘uzlah wajib dilakukan jika seorang hamba ingin serius menempuh perjalanan menuju sang kholiq. Beliau memaparkan ada dua alasan kenapa seorang hamba wajib ber ‘uzlah. Pertama, lingkungan dan masyarakat akan membuat lalai akan kewajiban seorang hamba. Kedua, banyak ajakan riya’ dan mengunggulkan diri dalam kehidupan masyarakat, dan tentunya akan merusak konsentrasi dan kualitas dalam beribadah karena sesungguhnya setelah manusia menyibukkan kita, ia akan menghalangi dari ibadah dan bahkan menjerumuskan kita terhadap keburukan.
Lebih lanjut lagi dalam pembahasan ‘uzlah, al Ghozali mengklasifikasikan manusia menjadi dua macam. Pertama, orang yang tidak dibutuhkan oleh masyarakat dalam masalah ilmu dan hukum. Yang terbaik bagi orang semacam ini adalah menyendiri. Jadi, ia tidak bergaul (berinteraksi) dengan masyarakat kecuali untuk salat jum’at, berjamaah, salat id, dan majelis ilmu. Kedua, orang yang menjadi panutan di bidang ilmu pengetahuan, masyarakat membutuhkannya untuk menerangkan masalah agama, menjelaskan kebenaran, mengajak kepada perbuatan baik dengan perbuatan maupun ucapan dan sebagainya. Maka orang semacam ini tidak dibenarkan mengasingkan diri dari masyarakat, bahkan ia harus menempatkan diri ditengah-tengah mereka sebagai pemberi nasehat kepada masyarakat, pembela agama dan penyebar ilmu tentang hukum-hukum Allah.[3]
Berangkat dari pemaparan diatas, kami menariknya pada pertanyaan apakah ‘uzlah masih relevan pada era modern? Jawabannya adalah masih relevan. Kenapa? Berikut penjelasannya. Selain mengistirahatkan akal dan jasmani dari kelelahan duniawi, ‘uzlah memiliki banyak keutamaan seperti meningkatkan ketaqwaan, memberikan waktu untuk mengintropeksi diri dan lain-lain. Akan tetapi dalam pelaksanaanya, seorang harus menentukan peran siapa dirinya di masyarakat, jika ia merupakan seseorang yang tidak memiliki hajat melayani umat maka ia boleh ber ‘uzlah. Akan tetapi jika ia memiliki peran yang cukup vital dalam pemberdayaan masyarakat maka ia tidak diperbolehkan untuk ber’uzlah. Keduanya tentu mendapatkan jalan masing-masing dalam penghambaannya. Bagi seorang yang ber’uzlah maka “jalan sepi” lah yang mengantarkannya kepada ridlo-Nya, dan bagi seorang yang berkhidmah menjadi pelayan masyarakat maka itulah jalannya dalam meraih ridlo-Nya karena ia termasuk golongan orang yang dicintai oleh Allah.
أحبُّ الناسِ إلى اللهِ أنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ، وأحبُّ الأعمالِ إلى اللهِ عزَّ وجلَّ سُرُورٌ يدْخِلُهُ على مسلمٍ،…الحديث[4]
Penerapan ‘uzlah masa salaf pada era modern ini tentu sangat berat jika dilakukan secara langsung, maka dalam pelaksanaanya kita bisa memulai sedikit demi sedikit dengan sesuatu yang mudah nan sederhana seperti ‘uzlah hati, yaitu dengan menjaga hati dari ketergantungan duniawi seperti pujian, harta dan gelar. Lalu untuk membatasi hiruk pikuk dunia kita bisa melakukan puasa medsos dengan menetapkan waktu untuk tidak memakai gadget, dan dengan cara-cara positif lain yang bisa membuat kita fokus beribadah dan mencegah kita dari kemaksiatan.
[1] Ahmad bin Muhammad bin ali, misbah al munir, hlm. 254
[2] ‘alawi abu bakr muhammad al kaff, mukhtashor ihya’ ulum al din, hlm. 95
[3] Abu hamid Al-ghozali, Minhaj Al- Abidin hlm 15
[4] Diriwayatkan oleh imam at thobroni dalam kitab al awsath wa al shoghir