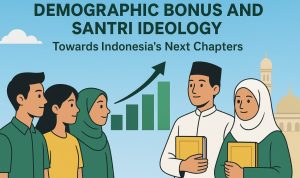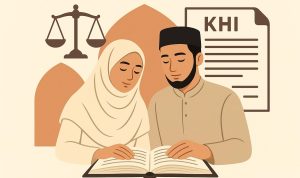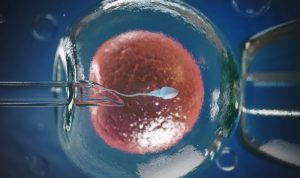Pendahuluan
Di Indonesia, khususnya masyarakat Jawa; tradisi nyumbang merupakan sebuah kebiasaan dalam memberikan sumbangan uang saat acara hajatan; seperti pernikahan, khitanan dan slametan, sebagai simbol kebersamaan, kepedulian dan solidaritas sosial antar warga. Namun seiring berjalannya waktu, tradisi tersebut mengalami pergeseran makna menjadi sistem timbal-balik yang menuntut pengembalian, berdasar pada siapa yang memberi dan nominal yang diberikan. Dalam praktinya, amplop tersebut diberikan tulisan nama pemberi dengan harapan sumbangan tersebut akan dibalas atau dikembalikan yang sepadan di kemudian hari.
Dengan demikian, ketika tradisi nyumbang berubah menjadi sistem balas-membalas, maka makna yang terdapat dalam pemaknaan simbol diatas menjadi hilang. Tradisi yang awalnya dimaknai sebagai simbol solidaritas sosial, berubah menjadi tuntutan yang bersifat transaksional. Hal ini bisa menimbulkan tekanan sosial, terutama bagi mereka yang kurang mampu dalam memenuhi tuntutan pemberi. Oleh sebab itu, tulisan ini bertujuan untuk meninjau bagaimana Fiqh Muamalah memandang fenomena tersebut. Sebab, sebagai sebuah tradisi yang berkembang di masyarakat, pelaksanaan hajatan seharusnya berlandaskan pada nilai-nilai Islam serta norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat.
- Tradisi nyumbang: Simbol kebersamaan, kepedulian dan solidaritas sosial
Pada masyarakat Jawa, dahulu tradisi nyumbang memiliki simbol yang kuat dalam makna kebersamaan, kepedulian dan solidaritas sosial; di mana masyarakat secara sukarela saling membantu ketika ada anggota keluarga atau tetangga yang menggelar acara hajatan seperti pernikahan, khitanan, atau selamatan. Sumbangan yang diberikan biasanya berupa hasil panen, seperti beras, singkong, atau buah-buahan.
Namun seiring berkembangnya zaman, sumbangan yang awalnya diberikan dari hasil panen, berubah menjadi uang tunai. Perubahan tersebut dikarenakan kepraktisan dalam pemanfaatannya. Tidak sampai situ, dalam prakteknya pemberian tersebut diberikan melalui amplop yang kemudian dituliskan nama pemberinya. Tradisi inilah, yang menimbulkan pemikiran bahwa siapapun yang pernah menyelenggarakan hajatan dan menerima sumbangan harus ganti menyumbang. Hal ini dilakukan agar saat seseorang ingin menyelenggarakan hajatan, maka ia akan memperoleh sumbangan dan uangnya kembali.[1]
Tradisi nyumbang semacam itulah yang kemudian memicu pergeseran makna dan memunculkan dinamika sosial baru, dimana sumbangan yang pada dasarnya merupakan perwujudan kebersamaan, kepedulian dan solidaritas sosial secara sukarela. Kini, menjadi aktivitas transaksional atau bahkan dianggap sebagai hutang sosial. Tidak jarang, masyarakat merasa terbebani dalam mengembalikan apa yang mereka dapatkan ketika di sumbang, dan juga ketika banyak undangan; terkhusus pada masyarakat yang kurang mampu. Namun dalam kenyataanya, tradisi tersebut tetap berjalan; meskipun dalam pelaksanaannya sedikit banyak menimbulkan kesulitan.
Dalam Islam, tradisi nyumbang memang tidak diatur secara eksplisit terkait pemberian sumbangannya. Akan tetapi, Islam menjelaskan terkait tujuan dari pelaksanaan dari sebuah hajatan; yang mana merupakan wujud dari rasa syukur atas diadakannya acara sakral dalam kehidupan seseorang.[2] Sebagai suatu tradisi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, tentunya pelaksanaan hajatan juga harus sejalan dengan aturan Syari’at, meskipun saat ini dalam pelaksanakannya sedikit-banyak terasa berat karena adanya akulturasi budaya. Namun, baik-buruknya tradisi ini, dalam kenyataannya tradisi tersebut masih tetap bertahan dan tentunya tidak bertentangan dengan Syari’at. Dan tujuan akhirnya pun tetap, yakni tolong menolong dan mempererat silaturrahmi antar warganya. Dengan demikian, berdasar pada kemaslahatan yang terkandung dalam tradisi tersebut, dan dirasa maslahat lebih besar dari pada kemadlorotannya, maka tradisi nyumbang masih dikategorikan sebagai ‘urf shahih (tradisi yang sah dan baik).
- Nyumbang dalam fiqh muamalah: antara hibah dan qardh.
Fiqh muamalah merupakan aturan-aturan hukum yang ditetapkan guna mengatur manusia dalam melakukan tindakan atau aktivitas duniawi dan sosial tertentu. Misalnya, dalam persoalan jual-beli, pinjam-meminjam, ataupun kerja sama. Hukum asal segala bentuk muamalah adalah mubah (boleh), berdasarkan pada kaidah al-aslu fil muʿāmalāti al-ibāḥah yang berarti segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya.
Pembahasan terkait persoalan muamalah sebenarnya sudah ada sejak zaman Nabi, kemudian pada masa selanjutnya; yakni para Imam Madzhab Fiqh, pembahaasan tersebut diperluas dan disistemasikan. Semakin berkembangnya zaman, perubahan merupakan suatu keniscayaan yang tidak bisa dipungkiri. Sehingga muncul problematika-problematika baru yang menuntut adanya ketentuan hukum baru, misalnya saja dalam permasalahan muamalah.[3]
Dalam perspektif muamalah, tradisi nyumbang bisa termasuk dalam akad tabarru’ (transaksi nirlaba yang tidak mencari keuntungan) berjenis hibah ataupun qardh. Sesuai dengan tujuan (niat) orang yang memberi, atau jika tidak diketahui tujuannya; maka dikembalikan pada adat kebiasaan yang berlaku di daerah tersebut.[4] Berikut penjelasannya;
- Hibah
Dalam kitab al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh, Wahbah az-Zuhaili mendefinisikan hibah sebagai suatu akad yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan barang kepada pihak lain tanpa adanya ganti dan dilakukan ketika masih hidup. Dengan demikian, sumbangan yang diberikan dalam hajatan dihukumi hibah, apabila pemberi memberinya dengan Cuma-Cuma dan tidak menuntutnya kembali atau di daerah tersebut tidak terdapat adat kebiasaan mengembalikannya.
- Qardh
Dalam kitab al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh, Wahbah az-Zuhaili mendefinisikan Qardh sebagai suatu akad yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan barang kepada pihak lain yang mewajibkan pengembalian tanpa adanya tambahan.[5] Dengan demikian, sumabangan yang diberikan dalam hajatan dihukumi Qardh, apabila pemberi menuntutnya kembali atau didaerah tersebut terdapat adat kebiasaan mengembalikannya.
Kesimpulan
Dengan memperhatikan niat serta kebiasaan (‘urf) masyarakat setempat, pemberian sumbangan yang bersifat sukarela tanpa harapan balasan atau timbal balik yang berarti sebagai bentuk solidaritas sosial dan mempererat silaturahmi, dalam perspektif fiqh muamalah dihukumi sebagai hibah, namun apabila pemberi sumbangan atau kebiasaan masyarakatnya menuntut pengembalian (timbal-balik), maka dihukumi sebagai qardh.
Daftar Pustaka
Az-Zuhaili, Wahbah. al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh, jilid 5. Damaskus: Dār al-Fikr, 2011.
Syatho al-Dimyati, Sayyid Abu Bakar ibn Muhammad. I’anah al-Thalibin ‘ala Hall Alfazh Fath al-Mu’in, juz III, 48.
Ningsih, Prilla Kurnia. Fiqh Muamalah. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021.
Saiin, Asrizal, Pipin Armita, Afriadi Putra, dan Bashori Bashori. “Tradisi Pemberian Sumbangan dalam Hajatan Pernikahan Perspektif Fiqhul Islam.” TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum 1, no. 2 (2020): 59–72. https://doi.org/10.35961/teraju.v1i02.47.
https://lirboyo.net/hukum-amplop-kondangan-termasuk-hutang-atau-hadiah/.
[1] Asrizal Saiin, Pipin Armita, Afriadi Putra, dan Bashori Bashori, “Tradisi Pemberian Sumbangan dalam Hajatan Pernikahan Perspektif Fiqhul Islam,” TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum 1, no. 2 (2020): 62.
[2] Asrizal Saiin, Pipin Armita, Afriadi Putra, dan Bashori Bashori, “Tradisi Pemberian Sumbangan dalam Hajatan Pernikahan Perspektif Fiqhul Islam,” TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum 1, no. 2 (2020): 69.
[3] Prilla Kurnia Ningsih, Fiqh Muamalah (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021), 17.
[4] Sayyid Abu Bakar ibn Muhammad Syatho al‑Dimyati, I’anah al‑Thalibin ‘ala Hall Alfazh Fath al‑Mu’in, Juz III, 48.
[5] Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh, Jilid 5 (Damaskus: Dār al-Fikr, 2011), hlm. 385.