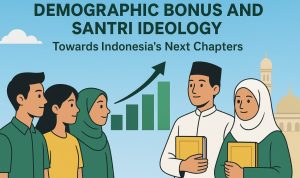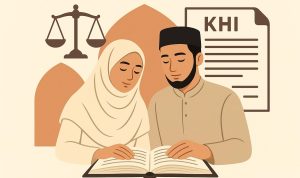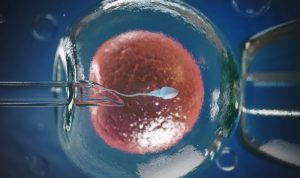Pernikahan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Dalam Islam, pernikahan bukan sekadar hubungan lahir antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebuah akad yang sakral dengan nilai ibadah. Akad ini memiliki dimensi spiritual, moral, dan sosial yang diatur secara rinci oleh hukum Islam untuk menjaga hak-hak para pihak yang terlibat. Salah satu unsur penting yang menentukan sah atau tidaknya pernikahan adalah keberadaan wali nikah, khususnya bagi mempelai perempuan. Di Indonesia, aturan ini secara formal tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan banyak merujuk pada fiqh madzhab Syafi’i yang merupakan mazhab dominan di masyarakat.
Dalam struktur hukum pernikahan, KHI menetapkan adanya lima rukun yang harus dipenuhi agar suatu pernikahan sah menurut syariat Islam, yaitu: calon suami, calon istri, dua orang saksi, dan ijab-qabul. Wali yang sah menurut KHI harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti berjenis kelamin laki-laki, beragama Islam, baligh, berakal sehat, dan berasal dari garis keturunan ayah (wali nasab). Urutan wali nasab dimulai dari ayah kandung, kemudian kakek, saudara laki-laki, dan seterusnya sesuai ketentuan ashabah. Jika wali nasab tidak ada, tidak memenuhi syarat, atau menolak menikahkan, maka kewenangan berpindah kepada wali hakim yang ditunjuk oleh negara. Selain itu, KHI juga menegaskan pentingnya pencatatan pernikahan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagai langkah administratif untuk memberikan perlindungan hukum bagi istri, anak, dan keberlangsungan keluarga.[1]
Dalam madzhab Syafi’i, pernikahan dianggap sah apabila memenuhi seluruh syarat dan rukun yang telah ditetapkan. Adapun rukun nikah terdiri dari lima unsur pokok, yaitu calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, dan sighat (ijab-qabul). Keberadaan wali dalam hal ini dipandang sebagai syarat mutlak yang tidak dapat diabaikan. Pandangan ini didasarkan pada dalil-dalil al-Qur’an dan hadis, salah satunya sabda Nabi: “Tidak sah nikah kecuali dengan wali.” Dalam madzhab ini, urutan wali nikah mengikuti prinsip ashabah, dimulai dari ayah kandung, kakek, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, dan seterusnya. Apabila semua wali nasab tidak ada atau tidak memenuhi syarat, maka hak perwalian berpindah kepada wali hakim.[2] Pandangan Imam Syafi’i ini juga dipengaruhi oleh kondisi sosial pada masanya, dimana perempuan sering dinikahkan pada usia muda dan dianggap membutuhkan perlindungan hukum melalui peran wali.
KHI dan fiqh Syafi’i memiliki kesamaan mendasar, yaitu menempatkan wali sebagai rukun nikah yang wajib ada, sehingga tanpa wali, pernikahan dianggap tidak sah. Perbedaan di antara keduanya lebih terlihat pada aspek administratif. KHI menambahkan kewajiban pencatatan pernikahan sebagai syarat legalitas di mata negara, sedangkan fiqh Syafi’i tidak menjadikan pencatatan sebagai unsur esensial, meskipun pada prinsipnya tetap menganjurkan keteraturan dalam pelaksanaan akad.
Dengan demikian, baik KHI maupun fiqh Syafi’i sama-sama berupaya menjaga kemaslahatan, melindungi hak-hak perempuan, serta memastikan bahwa pernikahan berjalan sesuai prinsip syariat Islam. Perbedaan pendekatan keduanya menunjukkan bahwa hukum Islam dapat diimplementasikan dengan penyesuaian terhadap konteks sosial dan kebutuhan masyarakat, tanpa meninggalkan prinsip dasar yang telah digariskan oleh nash.
[1] Marzuki Wahid, Fiqh Indonesia, (Cirebon: ISIF, 2014).
[2] Zainuddin al-Malibari, Fath al-Mu’in.