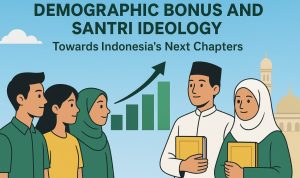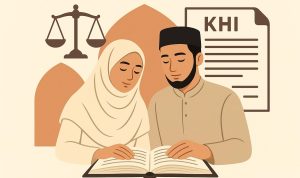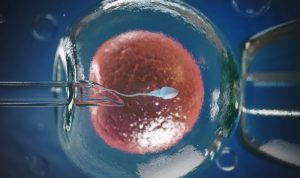Pendahuluan
Pernikahan merupakan peristiwa penting yang sakral dalam kehidupan seorang laki-laki dan perempuan, yang dengannya mengikat suatu hubungan lahir-batin sebagai suami istri; sebagaimana tercantum dalam UU RI No. 1 Tahun 1974. Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya’ Ulum ad-din menyebutkan 3 alasan mengapa pernikahan menjadi sebuah peristiwa penting, pertama pernikahan adalah cara manusia melestarikan dan mengembangbiakkan keturunan dalam rangka melanjutkan kehidupan manusia di bumi. Kedua, pernikahan menjadi cara manusia menyalurkan hasrat seksual, dan menjaga alat kelamin. Ketiga, pernikahan menjadi tempat seseorang menumpahkan keresahan hati dan membebaskan diri dari kesulitan hidup secara terbuka kepada pasangannya.[1] Dalam Islam tujuan pernikahan salah satunya telah disebutkan dalam al-Qur’an, yaitu surah ar-rum : 21
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بيَنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحمَةً إِنَّ فِي ذَلكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يتَفَكَّرُونَ
Dalam ayat di atas, dapat kita temukan poin-poin tujuan dari sebuah pernikahan yaitu menentramkan jiwa (sakinah), cinta (mawaddah), dan kasih sayang (rahmah). Ketiga poin tersebut, menjadi prinsip yang harus dipahami dan dipegang teguh oleh kedua belah pihak, suami dan istri. Dengan demikian, pernikahan bukan sekedar tempat memuaskan nafsu seksual saja, namun juga membangun hubungan yang damai dan saling menghargai.
Dan untuk mencapai tujuan tersebut, Islam telah mengatur dan mengarahkannya dalam berbagai bentuk, seperti syarat dan rukun pernikahan, serta hak dan kewajiban suami-istri. Mahmud Syaltut dalam bukunya Akidah dan Syari‘ah Islam menawarkan lima prinsip sebagai prosedur yang harus dipenuhi dalam pembinaan keluarga pada fase pranikah. Pertama saling mengenal dan memahami (atta‘aruf) di antara kedua mempelai. Kedua adalah al-ikhtibar yaitu tahap penjajakan yang dilaksanakan dengan melakukan khitbah. Ketiga ar-rida (kerelaan), Keempat kafa’ah yaitu kesejajaran antara kedua mempelai, Kelima mahar atau mas kawin.[2]
Dari pernyataan diatas, konsep kerelaan atau dapat diartikan sebagai persetujuan harus dijelaskan secara terperinci, sebab persetujuan memiliki dua subjek berbeda yang berpengaruh pada status hukumnya; yaitu gadis dan janda. Dalam hal ini, penulis mencoba menganalisis konsep pernikahan bagi perempuan; baik yang belum pernah ataupun sudah pernah menikah (janda), yang ditinjau dari batas usia, persetujuan dan peran wali menggunakan sudut pandang Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum normatif dan hukum positif yang mempunyai kekuatan hukum pemberlakuan dan Madzhab Syafi’i sebagai madzhab yang dominan dianut oleh masyarakat muslim Indonesia. Oleh sebab itu, perbandingan keduanya penting sebagai bentuk penggambaran positivisasi dari madzhab syafi’i dalam hukum di Indonesia dan upaya memformulasikan fiqh normatif yang berkelindan dengan zaman, sehingga lahirlah fiqh Indonesia.
A. Aspek Usia Minimal Pernikahan
Batas usia minimal pernikahan di Indonesia sebelum adanya perubahan, telah diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974, yang mana menjadi rujukan dalam ketetapan KHI Pasal 15 ayat 1; bahwa usia minimal pernikahan adalah 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Dan setelah adanya perubahan batas usia minimal pernikahan menjadi 19 tahun, baik laki-laki maupun perempuan; sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 16 tahun 2019 pasal 7. Perdebatan terkait batasan usia dalam konteks pernikahan menyangkut kesiapan dan kematangan seseorang, bukan hanya fisik, namun juga psikis, ekonomi, agama dan sosial-budaya. Hal ini karena pernikahan pada usia dini, seringkali menimbulkan berbagai resiko, terutama bagi kaum perempuan yang sering kali menjadi korban; dan resiko yang dialami tidak hanya bersifat biologis saja; seperti kerusakan organ reproduksi. Tapi juga resiko psikologis.
Sebenarnya, dalam hukum Islam tidak ada ketetapan secara eksplisit terkait batasan usia menikah. Namun, Madzhab Syafi’i memiliki pandangan terkait kebolehan atau anjuran bagi seseorang untuk melaksanakan sebuah pernikahan yang idealnya telah mencapai usia baligh, yang pada umumnya; usia baligh bagi laki-laki pada usia 15 tahun, dan bagi perempuan pada usia 9 tahun, dengan disertai menstruasi. Selain itu, juga melihat dari kedewasaan, kemampuan, dan kematangan seseorang dalam menjalani kehidupan pernikahanan. Hal tersebut, berdasar pada firman Allah SWT. Dalam surah an-Nisa ayat 6 :
وَابْتَلُوا الْيَتٰمٰى حَتّٰىٓ اِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَۚ فَاِنْ اٰنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوْٓا اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْۚ وَلَا تَأْكُلُوْهَآ اِسْرَافًا وَّبِدَارًا اَنْ يَّكْبَرُوْاۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوْفِۗ فَاِذَا دَفَعْتُمْ اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ فَاَشْهِدُوْا عَلَيْهِمْۗ وَكَفٰى بِاللّٰهِ حَسِيْبًا ٦
Ayat tersebut menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan pernikahan baik bagi perempuan maupun laki-laki, keduanya harus dilihat dari usia baligh dan kemampuan secara materi (pemeliharaan harta; dan apabila seseorang belum mampu, maka hendaklah berpuasa terlebih dahulu.
Bagi Madzhab Syafi’i, ketentuan-ketentuan diatas dikecualikan bagi seorang ayah atau wali yang menikahkan anak perempuannya yang belum baligh. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa Madzhab Syafi’i tidak menentukan batas usia minimal menikah secara eksplisit, namun lebih menekankan pentingnya kematangan dan kemampuan calon mempelai dalam menjalani kehidupan pernikahan. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan utama adalah seperti kematangan fisik dan mental, kemampuan untuk memahami hak dan kewajiban dalam pernikahan, dan kemampuan untuk menafkahi keluarga.
B. Aspek Persetujuan Pernikahan
Persetujuan calon mempelai sangat erat hubungannya dengan tujuan-tujuan dalam pernikahan (Maqashid Al-‘usrah), diantaranya adalah :
- Mengatur hubungan antara dua individu.
- Menjaga keturunan.
- Mewujudkan keluarga Sakinah, mawaddah, wa rohmah
- Menjaga nasab
- Menjaga agama dalam kehidupan keluarga
- Mengatur aspek aspek dasar keluarga
- Mengatur aspek ekonomi keluarga.[4]
Dalam KHI, persetujuan calon mempelai dalam pernikahan telah diatur dalam pasal 16 ayat 1 yang berbunyi “Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai” dan ayat 2 yang berbunyi “Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas”.[5] Yang mana pasal tersebut sudah sesuai dengan UU Nomor 1 pasal 6 ayat 1 tahun 1974, yaitu “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”.
Kemudian, ketentuan tersebut dijelaskan lebih rinci pada KHI pasal 17 yang berbunyi :
- Sebelum berlangsungnya perkawinan, Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu pesetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah.
- Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.
- Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.[6]
Pasal-pasal tersebut menekankan pentingnya persetujuan calon mempelai dalam sebuah pernikahan, terkhusus bagi perempuan yang biasanya menjadi korban pernikahan tanpa persetujuan atau bahkan pemaksaan. Dengan demikian, pernikahan tanpa izin atau persetujuan dari pihak mempelai dapat dibatalkan atau tidak dilanjutkan.
Dan berbeda dari KHI; Mazhab Syafi’i memperbolehkan pernikahan tanpa izin atau persetujuan dari calon mempelai sesuai ketentuan-ketentuan yang ditetapkan. Dalam hal ini, Madzhab Syafi’i lebih mengkaitkannya dengan eksistensi wali. Menurut Firman Arifandi, wali adalah orang yang memiliki kuasa dan wewenang atas wanita atau anak perempuan yang hendak melakukan akad nikah (Arifandi, 2019). Oleh sebab itu, pernikahan tidak sah tanpa adanya seorang wali (Hamzah, 2022). Madzhab Syafi’i mengelompokkan kebebasan atau persetujuan perempuan dalam pernikahan ke dalam tiga kelompok, yaitu gadis yang belum dewasa (di bawah 15 tahun dan belum menstruasi), gadis dewasa, dan janda (Ilma Asmawi & Muhammad Bakry, 2020)[7]
- Para ulama sepakat bahwa untuk pernikahan seorang wanita janda, baik sudah baligh ataupun belum baligh; diwajibkan adanya persetujuan. Namun, Berbeda dengan Madzhab Maliki dan Hanafi yang membolehkan memaksa janda yang belum baligh untuk menikah.
- Para Imam Madzhab sepakat bahwa untuk gadis kecil (belum baligh) diperbolehkan menikahkannya tanpa persetujuannya. Namun, mereka berbeda pendapat terkait siapa yang boleh menikahkannya. Menurut Madzhab Syafi’i yang boleh menikahkann tanpa persetujuannya adalah bapak dan kakeknya (wali mujbir), sedangkan Madzhab Maliki berendapat hanya bapak saja, atau orang yang dipasrahi oleh bapaknya untuk melakukan akad. Dan Madzhab Hanafi berpendapat bahwa setiap orang yang mempunyai hak wali terhadap gadis tersebut, maka diperbolehkan menikahkan tanpa persetujuannya. Namun, ketika sudah beranjak dewasa maka wanita tersebut mempunyai hak khiyar (memilih).
- Untuk gadis dewasa (sudah baligh), para ulama’ berbeda pendapat terkait persetujuannya untuk dinikahkan. Madzhab Syafi’i dan Madzhab Maliki berpendapat persetujuannya hanya sekedar Sunnah saja, sedangkan menurut Madzhab Hanafi, harus dengan persetujuan dari gadis tersebut. Dan diamnya seorang gadis dewasa, dianggap cukup sebagai persetujuan dinikahkan.[8]
C. Peran Wali dalam Pernikahan
Sahnya sebuah pernikahan, salah satunya dapat dilihat dari terpenuhi atau tidaknya rukun dalam pernikahan. Sebagaimana telah ditetapkan 5 poin rukun pernikahan dalam KHI Pasal 14, yang mana sesuai dengan ketetapan dalam Madzhab Syafi’i, yaitu; adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab-qobul. Pernikahan bukan sekadar peristiwa kontraktual biasa, melainkan ikatan sakral yang melibatkan tidak hanya kedua mempelai, tetapi juga keluarga besar masing-masing pihak. Oleh sebab itu, konsep wali dalam pernikahan memegang peranan penting, karena dianggap sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dan memahami kepentingan serta perlindungan bagi mempelai perempuan; lebih dari pihak lain mana pun. Karena itulah, keberadaan wali menjadi salah satu syarat sahnya pernikahan sebagaimana telah dipertegas dalam ketetapan KHI pasal 19, yang berbunyi “Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”.[9]
Kemudian, mengenai ketentuan siapa yang berhak menjadi wali nikah, KHI telah mengaturnya dalam pasal 20 ayat 1 : “Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh”.[10] Pasal tersebut secara eksplisit mengindikasikan bahwa hanya seorang laki-laki saja yang dapat berperan sebagai wali dalam pernikahan, ketentuan tersebut sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Madzhab Syafi’i, Dalam Madzab Syafi’i, kehadiran laki-laki menjadi wali dalam pernikahan juga menjadi salah satu rukun nikah, yang berarti tanpa kehadiran wali, maka pernikahan tidak sah.
Kemudian yang dimaksud wali nikah disini adalah terdiri dari wali nasab dan wali hakim, sebagaimana telah ditetapkan oleh KHI pasal 20 ayat 1 yang mana sudah sesuai dengan ketentuan yang dalam Madzhab Syafi’i. Syekh Jalāl ad‑Dīn al‑Maḥallī dalam Kanz al‑Raghibīn secara rinci mengurutkan urutan dalam wali nasab;
- Bapak kandung
- Kakek dari bapak
- Bapaknya kakek dari bapak (Eyang/Buyut)
- Saudara laki-laki sekandung (Sebapak Seibu) atau Saudara laki-laki sebapak
- Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung atau sebapak
- Saudara laki-laki sekandung atau sebapak dari bapak
- Anak laki-laki (Sepupu) dari saudara laki-laki sekandung atau sebapak dari bapak, dst.[11]
Tidak semua wali nasab memiliki hak ijbar (kekuasan menikahkan tanpa izin), atau biasa disebut dengan wali mujbir. Dalam kitab al-Fiqh ‘ala Madzahib al-Arb’ah, Madzhab Syafi’i berpendapat bahwa wali mujbir adalah bapak dan kakek. Sedangkan Madzhab Maliki dan Hambali berpendapat bahwa wali mujbir terdiri dari bapak saja, dan bisa diwakilkan oleh orang lain, dengan pemasrahan yang jelas. Berbeda dari ketiganya, Madzhab Hanafi menganggap semua wali memiliki hak ijbar. [12]
Dalam hal ini, KHI pasal 21 juga menjelaskan urutan terkait wali nasab yang terlebih dulu berhak menikahkan;
- Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu
didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calonmempelai wanita.
- Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
- Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
- Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.
2. Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
3. Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya, maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah karabat kandung dari kerabat yang seayah.
4. Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.[13]
Kemudian pada pasal KHI selanjutnya (pasal 22) , menjelaskan ketentuan-ketentuan sebagai wali nikah; yang berbunyi “Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.”[14] Dan apabila wali nasab berhalangan hadir atau wali menolak menjadi wali nikah (wali adlal), maka barulah wali nikah dapat diwakilkan oleh wali hakim; sebagaimana tercantum dalam pasal 23 ayat 1 & 2. Dalam hal ini, KHI juga sudah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Madzhab Syafi’i; sebagaimana di jelaskan dalam kitab Kanz al‑Raghibīn bahwa apabila berkumpul satu tingkatan wali nikah, maka disunnahkan lebih mendahulukan yang lebih paham agamanya, kemudian yang lebih tua atas dasar persetujuan dari calon mempelai. Dan seandainya wali nasabnya berhalangan, maka wali hakim dapat mewakilkannya.[15]
Kesimpulan
Pernikahan adalah institusi sakral yang diatur secara rinci dalam Islam dan hukum positif Indonesia. Dalam aspek usia, hukum positif melalui UU No. 16 Tahun 2019 menetapkan batas minimal 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan, sementara Madzhab Syafi’i menekankan pada kedewasaan (baligh dan rusyd), bukan usia tertentu. Dalam aspek persetujuan, KHI menegaskan pentingnya persetujuan dari kedua mempelai. Berbeda halnya dengan Madzhab Syafi’i yang memperbolehkan wali mujbir (ayah atau kakek) menikahkan gadis tanpa izin, dengan ketentuan tertentu. Sedangkan dalam aspek wali, KHI dan Madzhab Syafi’i menjadikan wali sebagai rukun sah pernikahan, dengan urutan dan syarat yang ketat.
Daftar Pustaka
al‑Maḥallī, Jalāl ad‑Dīn. Kanz al‑Raghibīn (Sharḥ Minhāj al‑Ṭālibīn). Damaskus: Dār al‑Fikr, 1405 H / 1985 M, hlm. 423.
al-Jazīrī, Abdurrahman. Al-Fiqh ʿalā al-Madhāhib al-Arbaʿah. Jilid IV. Beirut: Dār al-Fikr, 1990, hlm. 29–30.
Mahkamah Agung Republik Indonesia. Himpunan Peraturan Perundang‑Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam: Serta Pengertian dalam Pembahasannya. Edisi revisi. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011, hlm. 67. ISBN 978‑979‑19258‑2‑2
Muhammad, K.H. Husein. Fiqh Perempuan 2: Refleksi Kiai atas Khazanah Hukum Keluarga dan Islam. Yogyakarta: IRCiSoD, Desember 2024. ISBN 978‑623‑8108‑85‑5.
Rasya, Keanu. “Batas Usia Nikah Perspektif Imam Mazhab Fikih dan Pengaruhnya Terhadap Implementasi Hukum Perkawinan Indonesia.” Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 15 Februari 2023.
Samsudin, Zainul Alim. “Konsep Persetujuan Wanita Dalam Pernikahan Pandangan Ibn Qayyim al‑Jawziyah dan Kompilasi Hukum Islam.” Jurnal Kompilasi Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Cirebon, 5 Januari 2019, hlm. 3.
Ubaidillah, M. Abi Mahrus dan Ibnu Aly Ismail. “Persetujuan Calon Mempelai sebagai Syarat Perkawinan di Indonesia: Perspektif Maqashid al‑‘Usrah.” Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah 3, no. 2 (Juli 2022): 208–218, khusus hlm. 212.
Wahid, Marzuki. Fiqh Indonesia: Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia. Cetakan I. Bandung: Marja / Institut Studi Islam Fahmina, 2014, hlm. 388.
Sofiana, Neng Eri, dan Helma Nuraini. “Persetujuan Perempuan dalam Pernikahan: Antara Madzhab Syafi’i dan Realita di Indonesia.” SETARA: Jurnal Studi Gender dan Anak 5, no. 2 (Desember 2023): 50–57
[1] K.H. Husein Muhammad, Fiqh Perempuan 2: Refleksi Kiai atas Khazanah Hukum Keluarga dan Islam (Yogyakarta: IRCiSoD, Desember 2024), hal. 49-50
[2] Samsudin, Zainul Alim. “Konsep Persetujuan Wanita Dalam Pernikahan Pandangan Ibn Qayyim Al‑Jawziyah Dan Kompilasi Hukum Islam.” Jurnal Kompilasi Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Cirebon, 5 Januari 2019, hlm. 3.
[4] M. Abi Mahrus Ubaidillah dan Ibnu Aly Ismail, “Persetujuan Calon Mempelai Sebagai Syarat Perkawinan di Indonesia Perspektif Maqashid al-‘Usrah,” Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah 3, no. 2 (Juli 2022), hlm. 212
[5]Mahkamah Agung Republik Indonesia, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam, edisi revisi (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), hlm. 67.
[6] Ibid
[7] Neng Eri Sofiana dan Helma Nuraini, “Persetujuan Perempuan dalam Pernikahan: Antara Madzhab Syafi’i dan Realita di Indonesia,” SETARA: Jurnal Studi Gender dan Anak 5, no. 2 (Desember 2023): 50
[8] Zainul Alim Samsudin, “Konsep Persetujuan Wanita dalam Pernikahan: Pandangan Ibn Qayyim al‑Jawziyah dan Kompilasi Hukum Islam,” Jurnal Kompilasi Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Cirebon, 5 Januari 2019, 3.
[9]Mahkamah Agung Republik Indonesia, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam, edisi revisi (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), hlm. 68.
[10] Ibid
[11] Syekh Jalāl ad‑Dīn al‑Maḥallī, “Kanz al‑Raghibīn (Sharḥ Minhāj al‑Ṭālibīn)”, (Damaskus: Dār al‑Fikr, 1405 H/1985 M), hlm. 423.
[12] Abd al‑Raḥmān al‑Jaziri, Al‑Fiqh ‘alā al‑Madhāhib al‑Arbaʿah, jil. IV (Kairo: Dār al‑Fikr), hlm. 29–30
[13] Mahkamah Agung Republik Indonesia, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam, edisi revisi (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), hlm. 68.
[14] Ibid
[15] Syekh Jalāl ad‑Dīn al‑Maḥallī, “Kanz al‑Raghibīn (Sharḥ Minhāj al‑Ṭālibīn)”, (Damaskus: Dār al‑Fikr, 1405 H/1985 M), hlm. 424.