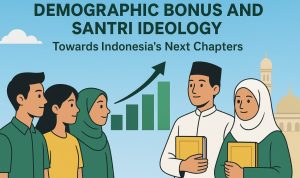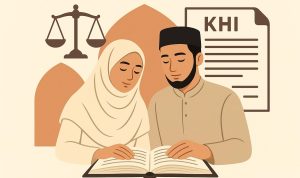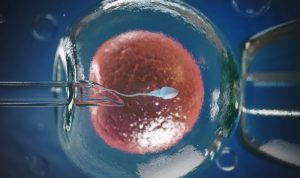Salah satu tantangan sosial terbesar di Indonesia adalah tingginya angka kemiskinan. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, Islam memiliki instrumen khusus yang dapat menjadi solusi, yakni zakat. Namun, menurut Kiai Sahal Mahfudh, zakat tidak seharusnya hanya diberikan secara konsumtif untuk memenuhi kebutuhan sementara, melainkan dikelola secara produktif agar mampu mendorong kemandirian ekonomi mustahik.
Zakat produktif pada dasarnya masuk dalam kategori zakat mal, namun pelaksanaannya berbeda dengan zakat yang lainnya. Zakat produktif yang memiliki perbedaan dengan zakat konsumtif itu keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mengurangi beban hidup orang miskin. Perbedaannya terletak pada bentuk pemberian zakatnya. Jika zakat yang secara konsumtif itu berbentuk pemberian langsung sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan pokok mustahik yang berkaitan dengan kebutuhan pokok sehari-hari. Istilah lainnya, zakat konsumtif adalah penyaluran harta zakat untuk kebutuhan habis pakai, sementara zakat produktif adalah penyaluran harta zakat yang akan memiliki efek ganda (multiplier effect) karena disamping dapat memenuhi kebutuhan pokok mustahik, juga dapat menghasilkan keuntungan yang terus menerus atau berkembang.[1]
Dalam gagasannya Kiyai Sahal pendayagunaan zakat secara produktif adalah pemberian zakat yang membuat orang yang menerima nya (mustahik) mampu menghasilkan sesuatu secara konsisten dengan harta zakat yang diterima, harta zakat yang diterima tersebut berupa alat kerja atau modal usaha yang akan bisa dikelola dan dikembangkan dalam jangka waktu yang Panjang.[2]Kiai Sahal Mahfudh mengenai tentang zakat produktif menekankan pentingnya pengelolaan zakat yang modern dan strategis agar berdampak signifikan terhadap pemberdayaan ekonomi umat Islam. Bagi Kiyai Sahal, zakat tidak cukup hanya diberikan dalam bentuk konsumtif, seperti memenuhi kebutuhan dasar sementara. Lebih dari itu, zakat dapat menjadi instrumen yang mendorong penerima untuk produktif dan mandiri secara ekonomi. Hal ini hanya bisa dicapai jika pengelolaannya dilakukan dengan manajemen yang profesional, mulai dari pendataan, pengumpulan, penyimpanan, hingga distribusi yang tepat sasaran. Dengan manajemen modern, zakat dapat tersalurkan secara efektif dan menciptakan perubahan nyata dalam kehidupan penerima.
Kiai Sahal tidak hanya membicarakan konsep ini secara teori, tetapi mempraktikkannya langsung. Dalam Nuansa Fiqh Sosial, beliau menceritakan pengalamannya membelikan becak untuk seorang tukang becak di Pati yang sebelumnya hanya menyewa milik orang lain. Setelah mendapat becak dari zakat, penghasilannya meningkat, bahkan ia mampu memiliki dua becak. Di desa lain, Kiai Sahal menginisiasi pengelolaan zakat melalui koperasi: mustahik menerima zakat dalam bentuk uang, yang kemudian dicatat sebagai tabungan modal usaha. Hasilnya, mereka mampu menciptakan pekerjaan baru dan meningkatkan pendapatan.[3]
Melalui pendekatan ini, Kiai Sahal menunjukkan bahwa zakat produktif tidak hanya mengurangi beban hidup mustahik, tetapi juga membangun kemandirian ekonomi. Meskipun kemiskinan tidak dapat dihapus sepenuhnya, langkah ini mampu memperkecil kesenjangan sosial. Lebih jauh, pendekatan ini merupakan implementasi nyata dari fikih sosial yang progresif—menafsirkan hukum zakat secara dinamis agar relevan dengan tantangan zaman.
Kesimpulan
Zakat produktif dalam pemikiran Kiai Sahal Mahfudh adalah upaya mentransformasikan zakat dari sekadar bantuan konsumtif menjadi sarana pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan. Kunci keberhasilannya terletak pada manajemen modern, pembinaan, dan pendampingan mustahik. Dengan demikian, zakat dapat menjadi instrumen keadilan sosial yang mendorong terciptanya masyarakat Muslim yang mandiri dan sejahtera.
[1] Hilmi Ridho dan Abdul Wasik, Zakat Produktif: Konstruksi Zakat nomics Perspektif Teoretis, Historis Dan Yuridis. (Malang: Literasi Nusantara. 2020). Hlm. 36
[2] Jamal Ma’mur. Jurnal RELIGIA Vol. 18 No. 1, April 2015.hlm.120
[3] Nuansa Fiqh Sosial,KH. MA. Sahal Mahfudh, LkiS Yogyakarta, 1994. Hlm-100-101.