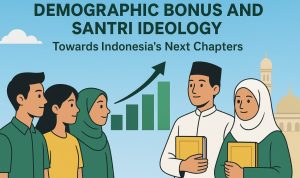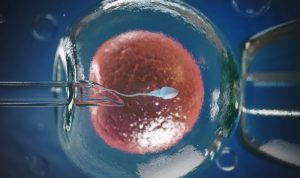Pendahuluan
Pernikahan merupakan akad suci dalam ajaran Islam yang tidak hanya berdimensi spiritual, tetapi juga sosial dan hukum. Sebagai ikatan mitsaqan ghalidzan, pernikahan memiliki tujuan luhur untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Saksi dalam pernikahan merupakan hal penting yang dapat mempengaruhi kebsahan menurut hukum Islam. Selain itu adanya saksi juga berfungsi sebagai langkah antisipatif apabila di kemudian hari terjadi konflik antara suami dan istri yang berujung pada proses hukum di pengadilan. Dalam fiqh madzhab Syafi’i perempuan tidak diperbolehkan menjadi saksi. Seiring perkembangan zaman, CLD-KHI memberikan konsep yang berbeda berdasarkan prinsip keadilan gender.
Persaksian Perempuan dalam CLD-KHI
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), saksi adalah orang yg melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa (kejadian).[1] Konsep perkawinan versi CLD-KHI, laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang setara dalam pernikahan maupun rumah tangga. Oleh karena itu perempuan boleh menjadi saksi dalam perkawinan. Hal ini karena CLD-KHI menghendaki kesetaraan antara laki-laki dan perempuan karena pada dasarnya peran, tanggung jawab dan haknya dianggap setara.
Sesuai dengan rumusan Tim Pengarusutamaan Gender Depag RI dalam Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam pasal 11 kaitannya dengan kesaksian seorang perempuan dalam perkawinan adalah sebagai berikut:
- Posisi laki-laki dan perempuan dalam persaksian adalah sama
- Perkawinan harus disaksikan sekurang-kurangnya oleh dua orang perempuan atau dua orang laki-laki atau satu orang laki-laki dan satu orang perempuan.[2]
Dalam naskah akademik CLD-KHI dijelaskan bahwa perumusan hukum keluarga Islam didasarkan pada prinsip keadilan gender, pluralisme, hak asasi manusia, dan demokrasi. Jika dikaji lebih mendalam mengenai praktik kesaksian perempuan dalam akad nikah, maka prinsip kesetaraan gender menjadi landasan utama bahwa tidak boleh ada perlakuan diskriminatif antara laki-laki dan perempuan. Semua individu dipandang setara, tanpa membedakan jenis kelamin, agama, ras, maupun bahasa.
Konsep saksi dalam CLD-KHI merupakan bentuk pemikiran yang bersifat transformatif, karena memberikan kesempatan kepada perempuan untuk menjadi saksi dalam akad nikah. Menurut salah satu perumus CLD-KHI, yaitu Siti Musdah Mulia, rumusan ini mencerminkan pandangan yang berpihak pada kesetaraan gender. Menurutnya, kesetaraan gender adalah kondisi yang menjamin adanya perlakuan yang adil bagi perempuan dan laki-laki. Kondisi tersebut harus dibangun dengan menghentikan segala bentuk diskriminasi yang selama ini diwariskan melalui norma-norma sosial dan budaya dalam masyarakat.[3]
Persaksian Perempuan dalam Fiqh Madzhab Syafi’i
Pernikahan merupakan momen yang sangat berarti dalam kehidupan manusia. Karena itu, banyak orang merayakannya dengan berbagai bentuk upacara dan tradisi. Mengingat pentingnya peristiwa ini, terdapat sejumlah syarat dan rukun yang wajib dipenuhi dalam prosesi pernikahan. Salah satu rukun tersebut adalah adanya saksi. Artinya, kehadiran saksi dalam pernikahan merupakan hal yang mutlak diperlukan. Tanpa kehadiran saksi, akad nikah dianggap tidak sah menurut mayoritas ulama.[4] Dalam kitab al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al-Arba’ah, ‘Abdurrahman al-Jaziri mengemukakan bahwa madzhab Syafi’i, Maliki, serta salah satu pendapat dalam mazhab Hanbali menolak kesaksian perempuan dalam akad nikah, perceraian, dan rujuk. Penolakan ini berlaku baik jika perempuan bersaksi bersama laki-laki maupun secara sendiri.[5] Pendapat mayoritas ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW.:
لانكاحَ إلاّ بوليّ وشاهدَيْ عدل. (رواه البيهقي عن عائشة)
“Tidak sah suatu pernikahan tanpa adanya seorang wali dan dua orang saksi yang adil”[6]
Kata شاهدي (dua orang saksi) dalam hadis ini menunjuk pada jenis kelamin laki-laki (mudzakkar).
Pendapat Imam Syafi’i tentang saksi nikah, sebagaimana Imam-imam yang lain, al-Syafi’i dan para pengikutnya juga punya pendapat tersendiri, salah satunya yang dijelaskan dalam kitab Al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al-Arba’ah sebagai berikut:
ولا يصح إلا بشاهدين ذكرين فإن عقد برجل وامرأتين لم يصح
Pernikahan hukumnya tidak sah kecuali disaksikan oleh dua orang saksi. Dan pernikahan hukumnya tidak sah tanpa disaksikan oleh dua saksi laki-laki. Maka ketika akad nikah disaksikan oleh satu laki-laki dan dua orang perempuan hukum pernikahan tidak sah.[7]
Dan dijelaskan pula dalam kitab al-Umm,
ويشهد على عقد النكاح شاهدان عدلان فإن نقص النكاح واحدا من هذا كان فاسدا
Akad nikah harus disaksikan oleh oleh dua saksi yang adil, ketika akad nikah kurang dari satu (hanya disaksikan oleh satu saksi) maka pernikahan hukumnya rusak (tidak sah).[8]
Menurut pandangan ulama mazhab Syafi’i, Maliki, dan Hanbali, kesaksian perempuan yang digabungkan dengan kesaksian laki-laki hanya dapat diterima dalam perkara yang berkaitan dengan harta, seperti transaksi jual beli, sewa-menyewa, hibah, wasiat, gadai, dan jaminan (kafalah). Alasan utama ketidakbolehan menerima kesaksian perempuan dalam perkara selain harta adalah karena perempuan dianggap lebih mudah terpengaruh oleh rasa belas kasihan, memiliki daya ingat yang kurang kuat, serta keterbatasan dalam otoritas sosial di berbagai aspek.[9]
Kesimpulan
Konsep kesaksian perempuan dalam CLD-KHI, dan fiqh madzhab Syafi’i menunjukkan adanya perbedaan dalam cara pandang terhadap hukum Islam. Fiqh Syafi’i memakai pendekatan yang lebih tekstual yang mana menganggap pernikahan sebagai ibadah yang suci, dan mewajibkan dua saksi laki-laki dalam akad nikah. Perempuan tidak diperbolehkan menjadi saksi karena dianggap tidak memenuhi syarat kesaksian. Sebaliknya, CLD-KHI memakai pendekatan yang lebih kontekstual dan modern. Dalam CLD-KHI, membolehkan perempuan menjadi saksi nikah, sebagai bentuk penerapan prinsip kesetaraan dan keadilan gender. Dari perbedaan ini, bisa disimpulkan bahwa fiqh Syafi’i lebih berfokus pada aturan klasik sedangkan CLD-KHI mencoba menyesuaikan hukum Islam dengan prinsip keadilan dan kesetaraan di zaman sekarang. Hal ini menunjukkan bahwa pembahasan terkait kesaksian perempuan tidak hanya soal hukum, tapi juga menyangkut keadilan sosial, terutama bagi perempuan di dalam keluarga.
[1] https://kbbi.web.id/saksi diakses pada tanggal 05 Agustus 2025 pukul 17.10 WIB.
[2] Marzuki Wahid, Fiqh Indonesia, (Cirebon: ISIF, 2014), 256.
[3] Siti Musdah Mulia, Membangun Surga di Bumi: Kiat-Kiat Membina Keluarga Ideal dalam Islam, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo,2011), 53.
[4] Sofyan, Zulkarnain Suleman, Fikih Feminis, (Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR,2014), 111.
[5] Abdurrahman al-Jaziri, Al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al-Arba’ah, Jilid IV (Beirut: Dar al-Fikr, 1970), 23-24.
[6] Imam al-Baihaqî, Sunan Baihaqi, Jilid VII (Beirut: Dar al-Ma’rifah), 111.
[7] Ibrahim bin Ali bin Yusuf al-Syaerazi Abu Ishaq, al-Muhadzab fi al-Imam al-Syafi’i, Jilid 2, 436.
[8] al-Imam Muhammad bin Idris al- Syafi’i, al-Umm, Jilid 5, 23.
[9] Nur Aisyah, “Kesaksian Perempuan”, Jurnal Al-Qadāu, Vol. 2. No. 2 (2015),180-181.