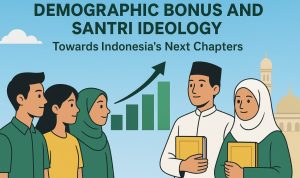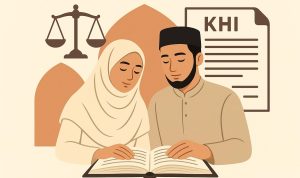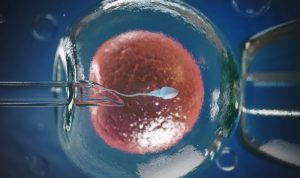Pendahuluan
Islam sebagai agama yang bersifat universal telah menyebar ke berbagai penjuru dunia, termasuk ke Nusantara. Islam hadir di Nusantara bukan melalui penaklukan militer, melainkan lewat pendekatan damai, yaitu perdagangan. Proses yang tidak melalui perusakan ini memungkinkan terjadinya integrasi nilai-nilai Islam dengan tradisi lokal yang telah ada sebelumnya, menciptakan bentuk ekspresi keislaman yang khas.
Di Indonesia, masuknya Islam tidak serta-merta menghapus tradisi yang sudah ada. Justru, banyak nilai-nilai lokal yang diberi makna baru dalam kerangka Islam. Proses ini dapat kita lihat dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari kesenian, upacara adat, hingga tata cara bermasyarakat. Salah satunya adalah tradisi sholawatan. Lebih dari sekadar pujian kepada Nabi Muhammad SAW, sholawatan merupakan jembatan antara nilai-nilai spiritual Islam dan kearifan budaya lokal.
Sholawatan sebagai Ekspresi Keislaman Nusantara
Tradisi sholawatan telah menyatu dalam kehidupan masyarakat Muslim Indonesia, khususnya di Jawa, Madura, dan Sumatra. Pembacaan sholawat tidak hanya dilakukan dalam pengajian dan majelis dzikir, tetapi juga dalam berbagai acara budaya seperti selametan, maulidan, bahkan dalam upacara pernikahan. Sholawat seperti Diba’, Simtuddurâr, dan Burdah dibacakan dengan iringan rebana, terbang, dan kadang gamelan menciptakan suasana yang menyentuh hati, memperkuat getaran spiritual sekaligus mempererat solidaritas sosial. Melalui sholawatan, masyarakat tidak hanya mengekspresikan kecintaan mereka kepada Nabi, tetapi juga merawat jati diri dan nilai-nilai lokal yang diwariskan turun-temurun.
Menurut ahli budaya Islam, Azyumardi Azra, Islam di Indonesia berkembang melalui jalur sufisme yang lekat dengan tradisi dan kebudayaan masyarakat setempat. “Islam yang berkembang di Indonesia bersifat inklusif, adaptif, dan mengedepankan pendekatan kultural,” ujarnya dalam salah satu tulisannya[1]. Sholawatan menjadi bukti konkret dari pendekatan tersebut: ia membumikan ajaran Islam melalui lisan dan rasa, bukan sekadar doktrin.
Sholawatan dan Peran Sosial Budaya
Budaya memiliki peran besar dalam menyampaikan ajaran Islam dengan cara yang lebih mudah diterima. Para wali songo adalah contoh bagaimana pendekatan kultural digunakan dalam menyebarkan Islam di Jawa. Sunan Kalijaga, misalnya, dikenal menggunakan wayang dan kesenian lokal sebagai media dakwah. Strategi ini membuat masyarakat tidak merasa teralienasi, melainkan justru merasa bahwa Islam dekat dengan kehidupan mereka sehari-hari.
Misalnya, dalam tradisi majelis sholawat, masyarakat dari berbagai lapisan sosial berkumpul, saling berinteraksi, dan mendapatkan siraman rohani. Selain itu, lantunan sholawat juga menjadi sarana pembelajaran bagi anak-anak dalam mengenal Islam secara menyenangkan. Fenomena ini memperlihatkan bahwa sholawat berfungsi sebagai jembatan edukatif antara Islam dan generasi muda.
Tradisi ini turut memperkuat identitas kultural umat Islam Indonesia. Seperti yang dikemukakan Clifford Geertz, kebudayaan merupakan sistem makna yang dimaknai secara kolektif[2]. Dalam hal ini, sholawatan menjadi simbol makna religius yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat, bukan hanya sebagai warisan masa lalu, tetapi juga bagian dari dinamika sosial hari ini.
Tantangan dan Dinamika Kontemporer
Meski memiliki akar kuat dalam budaya lokal, sholawatan juga menghadapi tantangan dari kelompok-kelompok yang menganggapnya bid’ah dan tidak sesuai dengan ajaran murni Islam. Pandangan ini lahir dari interpretasi yang kuat terhadap teks, tanpa melihat nilai-nilai moral, sosial, dan spiritual yang terkandung dalam praktiknya. Padahal, sebagaimana dinyatakan oleh KH. Mustofa Bisri (Gus Mus), “Sholawat adalah bentuk paling halus dari cinta. Dan cinta kepada Rasul adalah bagian dari iman.”[3]
Di sisi lain, tradisi ini menunjukkan dinamika positif. Inovasi sholawat modern seperti yang dilakukan oleh grup Sabyan Gambus atau majelis-majelis sholawat, seperti ahbabul mushtofa, az zahir, yang mampu menjangkau khalayak luas, termasuk anak muda urban. Ini membuktikan bahwa sholawatan adaptif terhadap zaman tanpa kehilangan nilai-nilai spiritualnya.
Penutup
Sholawatan adalah bentuk harmonisasi Islam dengan budaya lokal yang hidup, dinamis, dan penuh makna. Ia menjadi ruang spiritual sekaligus budaya bagi masyarakat Muslim Indonesia. Dalam konteks pluralisme dan tantangan globalisasi, pelestarian tradisi sholawatan merupakan bagian dari upaya mempertahankan identitas Islam yang damai, toleran, dan membumi. Sudah semestinya tradisi ini terus dirawat, dikembangkan, dan dijadikan bagian dari strategi dakwah yang relevan dengan zaman.
[1] Azra, Azyumardi. Islam Substantif: Fondasi Keagamaan dan Moral Bangsa. Bandung: Mizan, 2000.
[2] Geertz, Clifford. The Interpretation of Cultures. New York: Basic Books, 1973.
[3] Bisri, KH. Mustofa. “Sholawat dan Kesejukan Jiwa.” Ceramah dalam Majelis Maulid Simtuddurâr, Semarang, 2023.
Fahrizal Umam, Santri Aktif Semester 5.